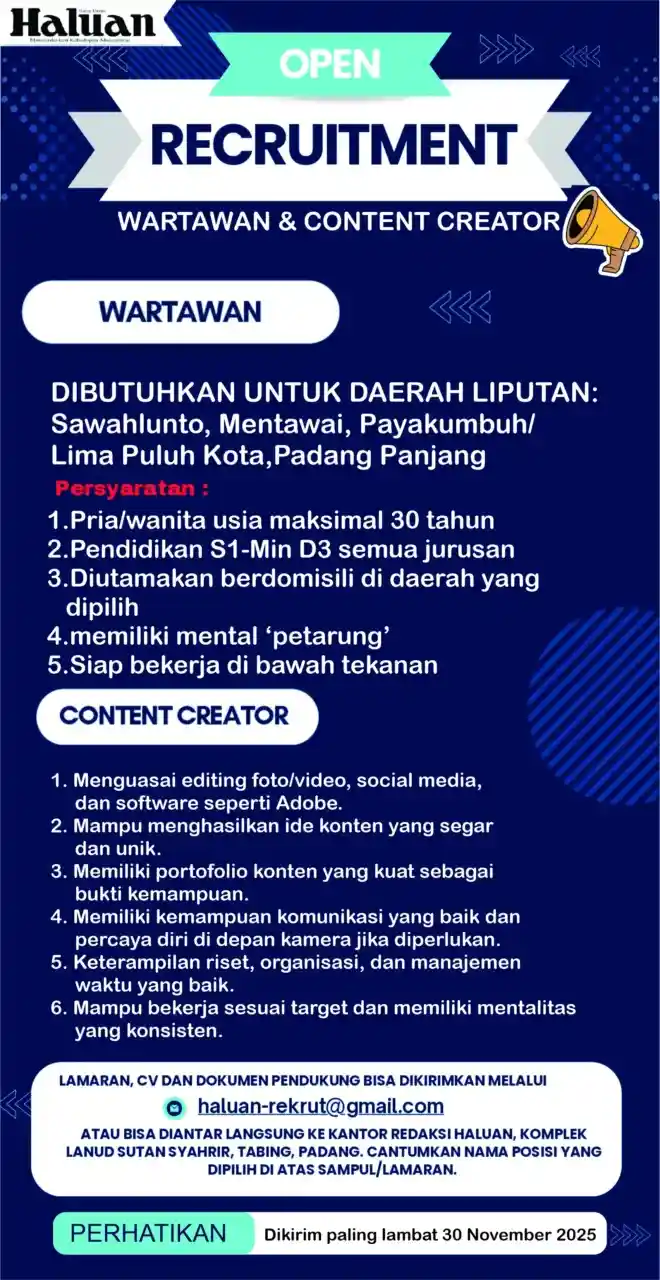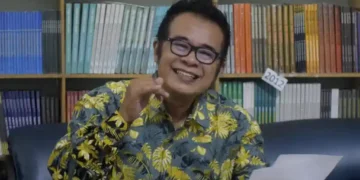Oleh:Elly Delfia
(Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas)
“Setiap bangsawan pasti priyayi namun sebaliknya, tidak semua priyayi itu bangsawan“(Arimi, 2008:2).
Kutipan di atas adalah bagian dari artikel Sailal Arimi (2008) yang berjudul “Pergeseran Kekuasaan Bangsawan Jawa Indonesia Analisis Wacana Kritis”. Artikel tersebut dimuat di Jurnal Masyarakat & Budaya. Memang sejak lama, suku yang terbilang dominan dalam membangun dan menguasai Indonesia salah satunya adalah suku Jawa. Suku ini tidak melulu isinya orang-orang tanpa kelas, tetapi juga diisi oleh masyarakat dengan kelas sosial. Salah satu kelas sosial tersebut disebut kaum bangsawan dan priyayi. Kaum bangsawan Jawa di zaman postmodern sekarang tidaklah hapus. Mereka tetap eksis. Hanya saja beberapa peran dan fungsinya mulai bergeser.
Artikel tersebut berbicara tentang kehidupan kaum priyayi pada masyarakat Jawa kekinian. Penulis memperpersoalkan kekuasaan bangsawan Jawa dengan status priyayi yang terus bergeser dari zaman ke zaman. Kaum priyayi disebut sebagai kelas menengah yang sudah ada sejak abad 19 dan 20 di Jawa. Mereka dikenal dengan rulling class (anggota birokrasi) yang memiliki kekuasaan istimewa dalam masyarakat. Kekuasaan tersebut diberikan dalam bentuk penghormatan tinggi untuk mereka karena mewarisi darah bangsawan. Keistimewaan bangsawan juga tercermin dari perbedaan ekonomi dan penggunaan bahasa antara kaum priyayi dan kawulo (kelompok masyarakat kelas bawah atau rakyat jelata). Penggunaan ragam bahasa disebut Geertz dengan high, middle, dan low. Dalam bahasa Jawa ragam bahasa ini disebut dengan krama atau ragam halus sangat sopan tinggi, madya atau menengah, dan ngoko atau ragam kasar (Arimi, 2008).
Ragam bahasa kaum priyayi berbeda dengan ragam bahasa masyarakat kelas di bawahnya. Krama dituturkan oleh priyayi dengan priyayi dan oleh kawulo kepada priyayi sebagai bentuk hormatan. Priyayi ada pada masa awal kerajaan-kerajaan di Jawa (Solo-Yogyakarta). Status priyayi merujuk kepada adik-adik dan kerabat raja karena raja hanya diwariskan kepada anak tertua. Sejak itu, masyarakat Jawa terbagi atas tiga strata, yaitu raja, priyayi, dan kawula. Pada masa awal, status priyayi diberikan tanpa pandang jabatan, prestasi, dan kedudukan. Priyayi mendapat kedudukan terhormat dan mulia pada mulanya. Lalu kekuasaan kaum priyayi mulai bergeser seiring dengan kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia. Status priyayi mulai bergeser menjadi mediator antara raja dan rakyat. Priyayi bertugas mengumpulkan upeti dari rakyat, mengorganisasi kerja bakti, dan memobiliasi rakyat, bahkan perilaku priyayi juga menyerupai perilaku hidup Belanda yang suka mabuk, memelihara anjing, dan tidak fanatik pada agama, seperti yang dijelaskan dalam artikel ini.
“Semakin lama pengaruh pemerintahan Hindia Belanda semakin kuat. Pada tahun 1830 dan setelahnya, kaum elit priyayi membangun identitas kepriyayiannya sebagai kelompok yang berafiliasi dengan keningratan bangsa kulit putih dengan pendidikan barat, kehidupan barat, dan bahasa Belandanya, bahkan priyayi cenderung kebelanda-belandaan. Mesranya hubungan dua bangsa berbeda ini mengukuhkan kembali posisi priyayi sebagai penguasa lokal dengan sebutan voolkshoofden (pemimpin rakyat) artinya pemimpin adat atau agama yang menyelesaikan masalah interen masyarakat (Onghokham, 2004:29). Sejalan dengan itu, Belanda menggunakan kaum priyayi untuk menjalankan birokrasi pemerintahan. Mereka menjadi media efektif untuk menghubungkan pemerintah penjajah dengan rakyat. Agar berjalan dengan optimal, birokrasi diawasi dan dikontrol secara ketat. Tidak cukup kontrol terhadap perkawinan, para pangreh praja juga diharapkan tidak fanatik terhadap agama (Islam), karena ini bisa menjadi benih timbulnya perlawanan terhadap bangsa kolonial. Priyayi yang suka minum dan memelihara anjing atau menunjukkan sikap sekuler seperti tidak menjalankan ibadah puasa, shalat,dan lain-lain lebih mudah naik jabatan dalam hierarki pangreh praja daripada yang fanatik (Arimi, 2008).
Pada masa pendudukan Jepang dan setelah kekalahan Belanda, afiliasi keningratan kaum priyayi kembali kepada keraton. Pada masa ini, terjadi rekonstruksi identitas priyayi dengan pengangkatan abdi dalem. Karena pengaruh nasionalisme, kaum terpelajar bisa menjadi priyayi pada masa ini. Pada masa prakemerdekaan dan orde lama, status kepriyayian bergeser lagi dari keturunan keluarga, terpelajar, dan diangkat. Pada masa orde baru, status kepriyayian bertambah lagi menjadi keluarga, terpelajar, diangkat, dan ketokohan, seperti penghargaan yang diberikan kepada keluarga Presiden Suharto yang berasal dari kawula atau keluarga petani menjadi priyayi.
Pada zaman reformasi, status priyayi masih ditentukan oleh keturunan keluarga, terpelajar, diangkat, dan ketokohan. Hanya saja terjadi pergeseran orientiasi loyalitas yang pada fase-fase sebelumnya mengacu pada kekuasaan pemerintahan, lalu pada masa reformasi orientasi loyalitas berpindah kepada humanitas atau nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, kekuatan dan pengaruh kekuasaan priyayi perlahan mulai memudar karena sikap mereka tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Saat ini, nilai-nilai kemanusiaan atau humanitas menjadi orientasi loyalitas penting pada kekuasaan kaum priyayi masyarakat Jawa. Loyalitas kaum priyayi Jawa saat ini ditentukan oleh seberapa tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keteladanan yang mereka miliki untuk pantas disebut sebagai seorang priyayi. Pemberian gelar priyayi dilakukan dengan upacara karena dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa kehidupan orang Jawa itu hampir seluruhnya di berisi upacara, mulai dari bangun pagi hingga malam hari.
Bagian menariknya adalah perubahan status priyayi dari zaman ke zaman yang dilihat dari kerangka toeri analisis wacana kritis Van Dijk (1996) yang menjelaskan relasi wacana dan kekuasaan. Lebih khususnya, bagaimana kekuasaan diperankan, diproduksi, dan dilegitimasi (Arimi, 2008). Analisis wacana kritis memandang: 1) bahasa berkaitan dengan kognisi sosial atau pikiran dan tindakan penuturnya (ranah linguistik); 2) narasi historis; 3) benda-benda yang berperan sebagai atribut, dan 4) kognisi sosial dan praktik kekuasaan. Dari perspektif linguistik, identitas kebangsawan dibedakan berdasarkan pemakaian tindak tutur (speech level), yaitu high, middle, dan low (krama, madya, dan ngoko). Pemakaian ngoko digunakan untuk kelompok berstatus di bawahnya, yaitu kawula dan menunjukkan relasi kekuasaan (power) dan pemakaian krama digunakan pada sesama bangsawan ditentukan oleh kesopanan (politness).
Selain itu, hal penting yang disampaikan adalah perkembangan identitas priyayi dari zaman ke zaman, mulai dari zaman kerajaan/prakolonial, zaman VOC (1602), zaman prakemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Pergeseran status gelar priyayi bangsawan Jawa merupakan komunitas yang hegemonik terhadap nilai-nilai budaya yang adiluhung dan alus. Masuknya unsur-unsur baru, baik keanggotaan baru, maupun nilai-nilai baru telah telah memunculkan diferensiasi dalam komunitas. Jenis pendidikan dan pekerjaan menjadi faktor penting dalam penataan sosial baru. Karakter dan ciri komunitas dari identitas priyayi makin bergeser. Kekuasaan kaum bangsawan makin melemah. Saat ini, mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi. Mereka hanya mempunyai kekuasaan budaya (penyelenggara upacara). Kekuasaan tersebut tidak lagi menjadi pengendali lapisan masyarakat yang lebih rendah atau kawula.
Pergeseran kekuasaan terjadi pada relasi intertekstual yang turut mengukuhkan kekuasaan priyayi. Ada teks yang memperjuangkan kelas kawula untuk menduduki kelas priyayi dan teks lain menegaskan kekuasaan priyayi keraton yang semakin melemah. Priyayi Jawa eksis dalam simbol-simbol kebudayaan, seperti rumah joglo, pakaian kebesaran, dan perlengkapan upacara. Mereka masih memiliki otoritas dalam mengelola simbol-simbol kebudayaan tersebut. Kawula dari petani tidak otomatis marjinal karena mereka hadir dalam struktur birokrasi dan ekonomi. Eksistensi trikotomi raja, priyayi, dan kawula mulai dipertanyakan dalam konsep negara kesatuan RI. Kekuasaan budaya keraton tidak lagi berasosiasi dengan kekuasaan. Kekuasaan yang ada sekarang adalah kekuasaan Sri Sultan dan rakyat.
Pergeseran paling kentara dari kekuasaan bangsawan Jawa terletak pada kekuasaan ekonomi dan politik yang disebabkan oleh pendidikan, pengaruh, dan kekayaan saat memperoleh identitas priyayi. Demikian cara pandang analisis wacana kritis dalam melihat pergeseran kekuasaan bangsawan Jawa. Analisis ini dapat diterapkan pada suku-suku lain di Indonesia karena pada masa-masa awal sebelum kemerdekaan, Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan yang memiliki kaum bangsawan. (*)