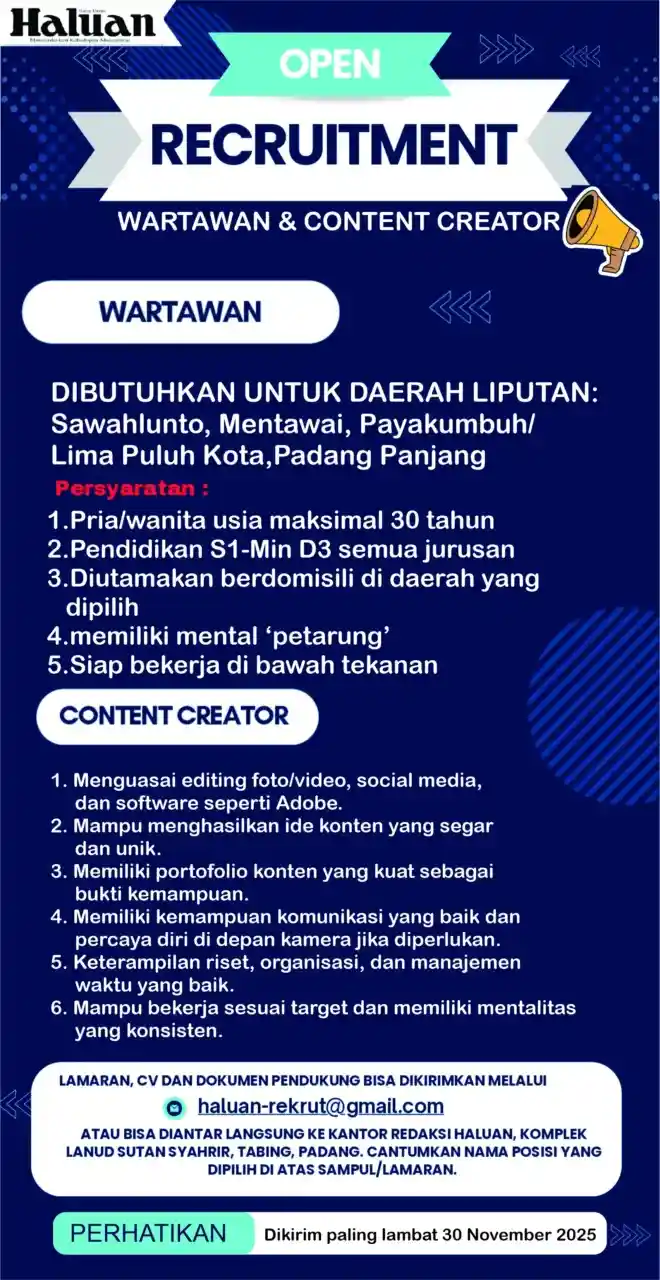Ia menyebut, kelompok kelas menengah justru menjadi salah satu yang paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini, bahkan stagnan sejak sebelum pandemi.
Untuk itu, Prof. Elfindri mengusulkan perlunya kesepakatan nasional soal garis kemiskinan. Ia tidak menolak penggunaan standar BPS, namun mendorong keterbukaan terhadap ukuran-ukuran baru dalam membaca kemiskinan dan kesejahteraan.
“Negara kita tidak perlu sungkan mempertahankan garis kemiskinan yang ada, tapi juga harus terbuka untuk mengadopsi perspektif lain. Bahkan Harvard punya indeks flourishing yang menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara paling bahagia,” tuturnya.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya membedakan antara kebahagiaan subjektif dan kemiskinan struktural. Banyak masyarakat miskin di Indonesia merasa hidup mereka sudah cukup layak, meski secara indikator ekonomi mereka masih tergolong miskin.
“Inilah tantangan besar dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi ke depan. Kita harus mampu menangkap realitas kemiskinan, bukan hanya lewat angka, tetapi juga melalui lensa sosial, budaya, dan psikologis masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai dinamika tersebut, Prof. Elfindri menekankan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan tidak cukup hanya mengandalkan data statistik, tetapi harus berpijak pada realita kompleks yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*)