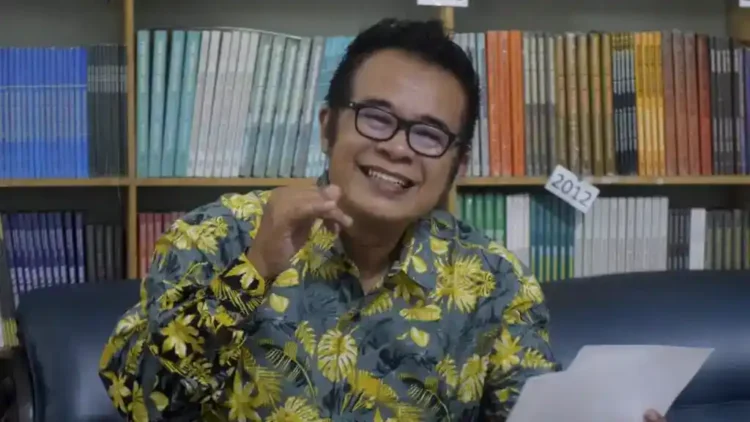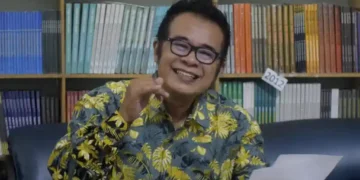Oleh:
Abdul Wachid B.S.
Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Saizu Purwokerto
Chairil Anwar bukan sekadar nama besar dalam sejarah sastra Indonesia, melainkan semacam cermin tempat kita menatap wajah keindonesiaan yang terus berubah. Ia hadir bukan hanya sebagai penyair yang mengguncang bahasa dan menembus batas kebebasan, tetapi juga sebagai simbol manusia merdeka yang mencari makna diri di tengah pergulatan zaman.
Puisi-puisinya lahir dari jiwa yang gelisah, tetapi justru di sanalah kita menemukan denyut kebangsaan yang jujur, berani, dan manusiawi. Membaca Chairil Anwar hari ini berarti menelusuri kembali hubungan antara puisi, kebebasan, dan identitas: tiga hal yang menjadi nadi bagi keberlanjutan kebudayaan Indonesia modern.
Namun, setiap zaman membaca Chairil dengan cara yang berbeda. Bagi generasi pasca-kolonial, ia adalah suara perlawanan; bagi generasi kini, mungkin ia lebih sering hadir sebagai ikon dalam buku pelajaran atau kutipan media sosial. Pergeseran ini wajar, sebab karya besar memang selalu lahir kembali di tangan pembacanya. Yang penting ialah bagaimana kita menafsir ulang semangat Chairil agar tetap hidup di tengah dunia yang kian bising oleh informasi, tetapi kian sunyi oleh refleksi.
Dalam esainya di Kompas.id, Nizar Machyuzaar mengangkat gagasan menarik: metafora Chairil seperti “aku ini binatang jalang” dan “aku ingin hidup seribu tahun lagi” telah menjadi jembatan yang terlalu sering dilalui, sehingga kehilangan kejutan dan vitalitasnya. Ia menyebutnya sebagai kematian metafora, sebuah istilah yang memancing perenungan baru.
Namun, benarkah metafora Chairil sudah mati? Ataukah justru masyarakat Indonesia hari ini yang kehilangan elan vital untuk menafsir ulang makna-makna Chairil secara kreatif dan progresif?
Chairil Anwar adalah tonggak penting dalam sejarah puisi Indonesia. Ia membuka jalan bagi ekspresi individualisme, keberanian eksistensial, dan semangat melampaui batas, sebuah karakter yang belum tentu nyaman dibaca oleh masyarakat Indonesia yang lebih menyukai harmoni sosial daripada teriakan “aku”-yang-luka. Dalam puisi “Aku”, Chairil menyatakan: “Aku ini binatang jalang // dari kumpulannya terbuang.” Kalimat ini menandai lompatan besar dalam sastra Indonesia karena memperkenalkan subjektivitas yang radikal dan otentik dalam konteks kolonial yang menindas.
Nizar menyebut bahwa frasa tersebut kini menjadi “metafora familiar” sehingga daya dorongnya menurun. Namun, metafora tidak mati karena sering digunakan. Ia hanya kehilangan daya gugah ketika pembaca berhenti mencari makna baru di dalamnya. Roland Barthes dalam Image-Music-Text menyatakan bahwa makna bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan “produk interaksi antara teks dan pembaca” (New York: Hill and Wang, 1977:147). Maka jika metafora Chairil terasa tumpul hari ini, bisa jadi karena kepekaan pembaca yang ikut tumpul terhadap tanda-tanda zaman.
“Aku” Chairil dan “Kita” Indonesia
Kita bisa membandingkan bagaimana Chairil membangun relasi dengan kata “aku” dan bagaimana negara kita mengelola konsep “kita”. Nizar mengajukan perbedaan antara kata penunjuk ini dalam “aku ini binatang jalang” yang menunjukkan kedekatan eksistensial, dengan kata penunjuk itu dalam frasa “bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” yang menunjukkan jarak.
Di sini, saya sepakat: Chairil menulis dari kedalaman rasa yang ia alami langsung, sedangkan negara sering berbicara dalam bahasa normatif dan impersonal. Artinya, bangsa ini membutuhkan Chairil-Chairil baru untuk menjembatani kembali antara cita-cita kemerdekaan dan kenyataan kehidupan rakyatnya.
Dalam konteks keindonesiaan hari ini, kita menghadapi paradoks yang tak kalah rumit: kebebasan telah dijamin secara konstitusional, namun ekspresi kritis sering kali dibungkam secara sosial atau politis. Chairil bisa hidup bebas dalam kata, karena ia menolak tunduk pada kekuasaan, baik kolonial, sosial, maupun budaya. Maka ketika kita memperingati seratus tahun Chairil, yang kita butuhkan bukanlah nostalgia terhadap puisi-puisinya, melainkan revitalisasi semangatnya dalam menghadapi zaman.
Chairil tak sekadar menulis puisi. Ia menulis hidupnya. Ia menolak hidup normatif; ia hidup seperti puisinya, terbuka, liar, tidak tunduk, dan menggugat. Itulah yang membuat puisinya tetap relevan jika dibaca secara aktif, bukan pasif. Dalam sajak “Karawang-Bekasi” (1948), Chairil menggabungkan nasionalisme dengan luka personal: “Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi/ tidak bisa teriak ‘Merdeka!’ dan angkat senjata lagi…”
Ia tidak menulis sebagai “pahlawan”, melainkan sebagai penyaksi dan pengemban luka kolektif. Di sinilah puisinya menjadi refleksi sosial-politik yang dalam. Keindonesiaan hari ini, yang penuh ambiguitas identitas dan tantangan kebangsaan, sangat membutuhkan puisi-puisi yang jujur semacam ini, yang berani bersuara bukan demi kekuasaan, tapi demi kemanusiaan.
Tafsir Ulang, Bukan Penguburan
Oleh karena itu, dalam menanggapi pendapat Nizar bahwa metafora Chairil bisa rapuh, buntu, atau terlalu familiar, saya justru melihatnya sebagai peluang. Familiaritas bukan berarti kehampaan, melainkan ajakan untuk menggali ulang. Paul Ricoeur dalam The Rule of Metaphor menegaskan: “Metaphor is the process by which the literal is replaced by the surprising” (London: Routledge, 1978:8). Maka tugas kita hari ini adalah memperbarui tafsir, bukan menguburkan metafora.
Sebagaimana Chairil mengguncang zaman kolonial dengan sajak-sajaknya, kini giliran kita mengguncang zaman digital yang serba cepat, dangkal, dan kehilangan spiritualitas. Chairil adalah pengingat bahwa puisi bisa mengubah kesadaran. Ia bukan hanya penggubah kata, tetapi juga penempuh jalan sunyi. Maka, seabad Chairil adalah panggilan untuk bangkit kembali, menulis, membaca, dan berpikir dengan keberanian.
Dengan begitu, metafora Chairil tak mati. Ia hanya menunggu kita menyapanya kembali, bukan dengan hormat kosong, tetapi dengan keberanian untuk menjadi “binatang jalang” di zaman yang jinak dan gaduh ini. (*)