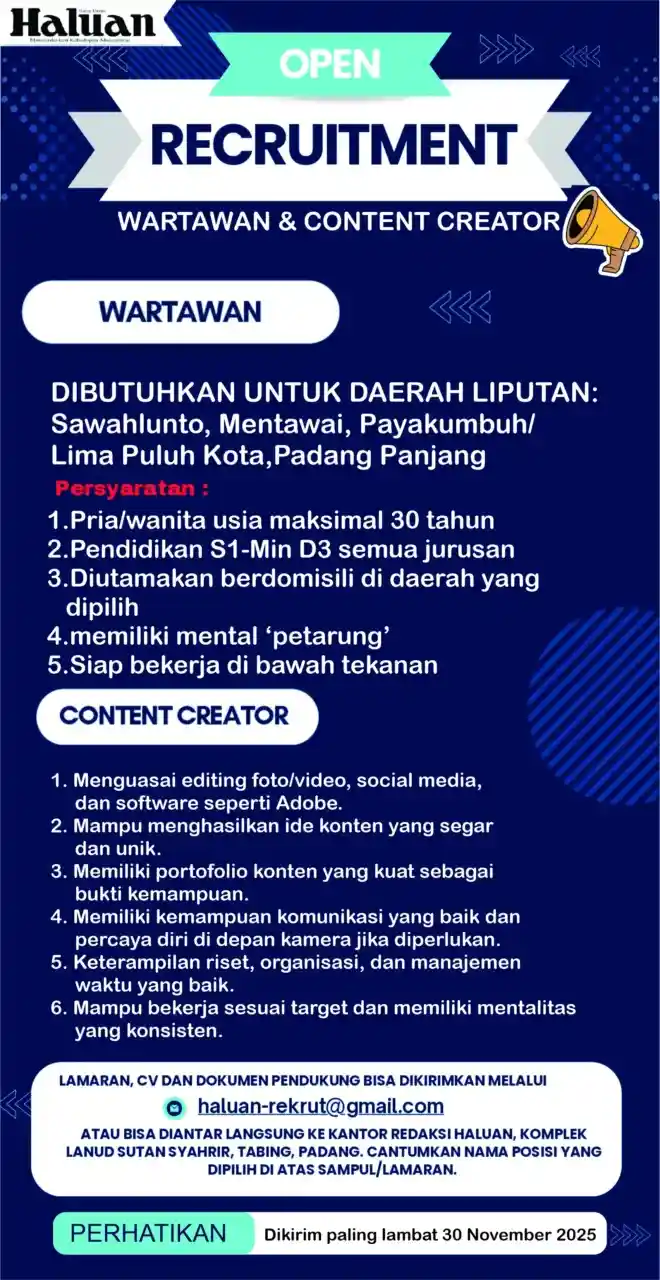Penulis : Enodiantasia Harahap, S. Psi
HARIANHALUAN.ID – Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki anak adalah salah satu faedah dalam perkawinan. Dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan yaitu mempertahankan keturunan agar dapat menjaga kuantitas peradaban manusia di dunia ini. Namun kenyataan nya tidak sedikit pula orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak mempunyai anak (Wahyu S., 2024).
Tema childfree akhir-akhir menjadi hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak untuk tidak diperbincangkan, masyarakat masih sering menganggap memiliki anak sebagai suatu keharusan, namun beberapa orang memilih jalan yang berbeda yakni memutuskan untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan yang mendasarinya (Malik & Magdalena, 2023).
Seperti AS, yang memilih Keputusan untuk childfree. Ia mengatakan bahwa “Keputusan saya memilih childfree karena saya merasa belum siap secara mental untuk menjadi orang tua. Saya sadar punya anak bukan hanya tentang melahirkan, tapi tentang mendidik dan membentuk manusia baru. Saya takut tidak bisa memberikan kasih sayang dan waktu yang cukup, jadi saya memilih tidak punya anak agar tidak melukai siapa pun.”
Fenomena ini mendapatkan ruang yang luas di media sosial dan literatur akademik global, di mana childfree telah menjadi bagian dari kebebasan reproduksi sejak 1970-an (Rizka & Yeniningsih, 2025). Dalam konteks Indonesia, Generasi Z tumbuh dalam era digital, menghadapi tekanan ekonomi, serta memperoleh akses informasi yang sangat luas, sehingga memengaruhi cara mereka mendefinisikan keluarga, kebahagiaan, dan identitas diri (Fuad et al., 2021).
Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini secara ilmiah guna melihat dinamika psikologis, sosial, dan nilai yang melatar belakanginya.
Fenomena childfree yakni keputusan sadar untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi mengalami peningkatan perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan Generasi Z Indonesia. Meskipun norma sosial Indonesia secara turun-temurun memandang memiliki anak sebagai tujuan utama perkawinan, kini semakin banyak individu muda yang mempertanyakan nilai tersebut.
Data Datain menunjukkan bahwa hanya 8,17 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap childfree, sedangkan 44,67 persen bersikap netral, mengindikasikan potensi perubahan nilai pada kelompok usia yang lebih muda (Farrencia, 2024).
Makna Childfree dalam Perspektif Generasi Z
Generasi Z menafsirkan childfree tidak sebagai bentuk penolakan terhadap keluarga, tetapi sebagai keputusan personal yang bersumber dari refleksi diri dan kesadaran akan tanggung jawab pengasuhan.
Banyak perempuan Gen Z mengakui bahwa mereka tidak memiliki dorongan untuk menjadi orang tua, bukan karena pengalaman negatif masa lalu. Seperti salah satu partisipan penelitian yang menyatakan bahwa ketidaksiapan mental dan kekhawatiran tidak mampu menjalankan peran pengasuhan menjadi pertimbangan utama dalam memilih childfree.
Hal ini sejalan dengan teori emerging adulthood yang dikemukakan Arnett (2000), yaitu masa ketika individu mengeksplorasi identitas dan nilai hidup (Arnett, 2000).
Teori Sistem Keluarga: Childfree sebagai Bentuk Diferensiasi Diri
Bowen (1978) dalam Teori Sistem Keluarga menjelaskan bahwa keluarga berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai dan harapan sosial. Di Indonesia, keluarga kerap menganggap anak sebagai indikator keberhasilan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, Generasi Z menunjukkan tingkat differentiation of self yang lebih tinggi, yakni kemampuan untuk mempertahankan keputusan pribadi meskipun bertentangan dengan harapan keluarga. Keputusan childfree pada konteks ini menjadi bentuk otonomi dan pencarian identitas yang independent (Brown & Errington, 2024).
Teori Peran: Negosiasi Ulang terhadap Peran Gender Tradisional
Menurut Biddle (1986) dan Eagly & Wood (2012), ekspektasi sosial terhadap perempuan sering dikaitkan dengan peran keibuan dan pengasuhan. Generasi Z menolak pandangan bahwa identitas perempuan harus ditentukan melalui fungsi reproduktif.
Penelitian Malik dan Magdalena (2023) menunjukkan bahwa perdebatan pro dan kontra mengenai childfree di masyarakat Indonesia masih sangat kuat, tetapi Gen Z lebih berani menegosiasi ulang peran gender tradisional dengan memilih jalur yang lebih selaras dengan aspirasi pribadi.
Keputusan childfree juga merupakan respons terhadap konflik peran modern, yaitu beban ganda antara karier dan pengasuhan yang terasa tidak realistis bagi sebagian perempuan muda.
Teori Identitas Diri: Childfree sebagai Proyek Reflektif Diri
Giddens (1991) menjelaskan bahwa identitas di era modern terbentuk melalui proses refleksi terus-menerus. Melalui konsep reflexive project of the self, keputusan childfree dilihat sebagai bagian dari usaha individu menentukan arah hidupnya berdasarkan nilai yang mereka anggap bermakna. Erikson (1968) juga menekankan bahwa konflik identitas pada masa dewasa awal dapat mendorong individu menentukan pilihan hidup yang unik dan otonom.
Bagi perempuan Gen Z, childfree adalah cara untuk mengekspresikan nilai-nilai seperti kebebasan, aktualisasi diri, dan keseimbangan hidup. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Gillespie (2003), yang menemukan bahwa perempuan childfree cenderung memaknai kebahagiaan melalui kualitas hubungan dan pencapaian personal, bukan melalui peran keibuan.
Terdapat berbagai faktor eksternal yang turut mendorong Gen Z memustuskan childfree.
Faktor Psikologis
Generasi Z cenderung lebih sadar terhadap kesehatan mental, tekanan emosional dalam pola pengasuhan, dan pengalaman masa kecil yang traumatis. Mereka memandang keputusan memiliki anak sebagai komitmen psikologis jangka panjang yang harus dipersiapkan, bukan kewajiban normatif.
Pertimbangan Ekonomi dan Karier
Kenaikan biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan sandang-pangan menjadi alasan rasional. Selain itu, orientasi karier dan kebebasan mobilitas juga menjadi aspek penting bagi Generasi Z yang lebih fleksibel dalam gaya hidup.
Pengaruh Media dan Globalisasi
Wacana internasional yang mengedepankan well-being, body autonomy, dan sustainable living turut membentuk pola pikir generasi muda melalui akses digital.
Konflik dengan Budaya dan Norma Lokal
Masyarakat Indonesia masih memegang paradigma bahwa keberhasilan seseorang diukur melalui pernikahan dan keturunan. Hal ini menjadikan individu childfree menghadapi stigma, tekanan keluarga, serta labeling sosial.
Fenomena childfree di kalangan Generasi Z Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam pemaknaan identitas, nilai hidup, dan konsep keluarga di era modern. Keputusan ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap tradisi, tetapi bagian dari proses refleksi diri untuk merancang masa depan sesuai nilai personal. Melalui perspektif teori sistem keluarga, teori peran, dan teori identitas diri, dapat dipahami bahwa childfree adalah bentuk otonomi, negosiasi ulang terhadap peran gender, dan upaya menata kehidupan berdasarkan tujuan personal.
Memahami fenomena ini secara ilmiah dan empatik menjadi penting agar masyarakat dapat menerima bahwa pilihan reproduksi adalah hak setiap individu. Di tengah perubahan sosial yang cepat, fenomena childfree memberi gambaran mengenai bagaimana generasi muda Indonesia mendefinisikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan makna hidup dalam konteks zaman. (*)