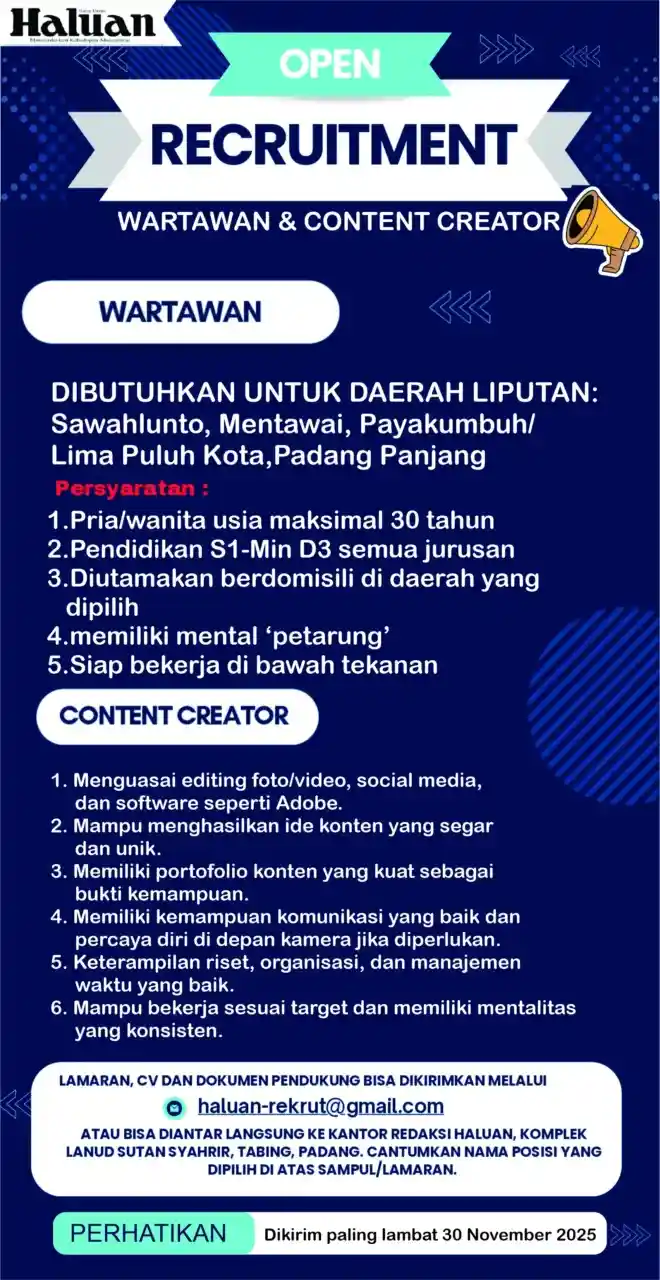Oleh: Rahmadiah (Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
PESISIR SELATAN – Siapa tak kenal Mandeh? Dijuluki “Raja Ampat-nya Sumatera Barat,” Mandeh menjadi ikon pariwisata yang menawarkan keindahan bahari dengan fasilitas modern. Namun, ironisnya, gemerlap pariwisata ini adalah bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), daerah yang menempati urutan kedua tertinggi dalam jumlah warga miskin di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Tinggal Landas yang Tak Tuntas
Kabupaten yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 218 km ini menghadapi paradoks pembangunan yang tajam. Di satu sisi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pessel terus meningkat, dari 70,84 (2022) menjadi perkiraan 72,02 (2024). Di sisi lain, persentase penduduk miskin justru naik kembali dari 7,11% (2022) menjadi 7,49% (2024).
Kesenjangan antara pertumbuhan simbolik dan kegagalan transformasi sosial-ekonomi ini menuntut kita meninjau ulang strategi pembangunan melalui lensa Teori Modernisasi.
Menurut teori modernisasi yang dipopulerkan oleh W. W. Rostow, pembangunan ekonomi harus melewati tahapan bertingkat, dengan tahap kunci adalah “take-off” (tinggal landas), di mana ekonomi mulai tumbuh cepat didorong oleh sektor unggulan.
Upaya pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh dan Pantai Carocok Painan jelas merupakan usaha Pessel untuk mencapai tahap take-offini, seperti yang disyaratkan Rostow bahwa masyarakat harus mampu melampaui hambatan tradisional.
Namun, apa yang disaksikan di Pessel adalah kegagalan modernisasi untuk menjadi kekuatan mainstream ekonomi. Pertama, terjadi modernisasi yang enclaving (terpusat), tidak merata, dan terisolasi.
Pembangunan infrastruktur dan investasi wisata hanya dirasakan di zona-zona tertentu, seperti Koto XI Tarusan dan pusat kabupaten. Sebaliknya, nagari-nagari di selatan, seperti Silaut dan Lunang, masih bergulat dengan keterbatasan akses dan layanan publik.
Ketimpangan spasial ini diperkuat oleh data. Meskipun sektor pariwisata menyumbang signifikan pada PDRB, lapangan kerja yang tercipta cenderung informal, musiman, dan memiliki upah rendah, jauh dari standar pekerjaan industri modern.
Sementara pusat kabupaten menikmati pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi, wilayah perdesaan yang bergantung pada sektor tradisional (pertanian/perikanan) terabaikan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Pessel juga menunjukkan bahwa mereka yang miskin cenderung jatuh lebih dalam, mengindikasikan bahwa stimulus ekonomi dari pariwisata tidak cukup kuat untuk mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan.
Fenomena ini adalah cerminan langsung dari kritik Teori Ketergantungan (Dependency Theory) terhadap Teori Modernisasi. Teori Ketergantungan menolak asumsi linearitas pembangunan Rostow dan berpendapat bahwa negara pinggiran (seperti Pessel dalam konteks regional) akan sulit mencapai “tinggal landas” sejati jika ekonominya didominasi oleh modal dari pusat (investor luar atau pusat provinsi/nasional).
Dominasi modal ini menciptakan ekonomi enclave yang mengeksploitasi sumber daya lokal tanpa mengintegrasikannya ke sektor-sektor produktif lainnya. Dalam konteks Pessel, pariwisata hanya beroperasi sebagai kantung ekonomi terpisah yang minim dampak multiplier effect pada petani, nelayan, atau industri kecil lokal, sehingga pertumbuhan yang terjadi hanya bersifat eksklusif.
Paradoks kenaikan IPM yang tidak seiring dengan penurunan kemiskinan menjadi bukti kuat bahwa pertumbuhan ekonomi Pessel tidak inklusif. Kenaikan IPM mungkin didorong oleh perbaikan akses dasar pendidikan dan kesehatan yang bersifat bertahap.
Sebaliknya, kenaikan angka kemiskinan menunjukkan sektor pariwisata gagal menyediakan lapangan kerja formal dan stabil.
Selain masalah struktural, pandangan Daniel Lerner juga menjadi kunci. Lerner menekankan bahwa modernisasi sejati adalah perubahan mentalitas, yang ia sebut “empathy”—kapasitas untuk siap berpartisipasi dan memahami pengalaman baru.
Secara sosiologis, basis adat nagari yang kuat dapat menjadi hambatan (traditional society) jika nilai-nilainya kaku terhadap mobilitas sosial, rasionalitas pasar, dan partisipasi publik yang menjadi prasyarat modernisasi.
Pembangunan fisik Mandeh tidak akan membawa transformasi jika mentalitas masyarakatnya tidak berubah, sebagaimana ditegaskan Lerner bahwa modernity is primarily a state of mind.
Lima Soal Utama Pessel
Berdasarkan analisis ini, dapat diidentifikasi lima masalah utama dalam proyek modernisasi Pessel. Pertama, modernisasi yang terjadi terlalu terpusat dan sektoral, hanya fokus pada pariwisata tanpa mentransformasi sektor tradisional (pertanian/perikanan).
Kedua, masalah ketimpangan spasial yang bersifat enclaving sangat nyata, di mana pertumbuhan terpusat di zona wisata sementara nagari terpencil tertinggal.
Lebih lanjut lagi, yang ketiga, modernisasi mentalitas yang tertunda karena penguatan SDM dan kualitas pendidikan belum optimal terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi modern (konsep empathy Lerner).
Keempat, daerah mengalami ketergantungan pada sektor tunggal sehingga ekonomi sangat rentan terhadap guncangan eksternal (terbukti pada masa pandemi).
Dan kelima, terjadi pertumbuhan tanpa transformasi sosial menyeluruh, dibuktikan dengan naiknya kembali angka kemiskinan meskipun IPM meningkat.
Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih berada di “titik ambang” take-off, sebuah proyek modernisasi yang “belum selesai.” Pertumbuhan berbasis pariwisata menghasilkan modernitas simbolik; ikon wisata, peningkatan kunjungan, fasilitas fisik; namun belum menghasilkan transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan terintegrasi.
Menanggapi kritik dependency theory, strategi fundamentalnya bertumpu pada lima pilar: Pertama, pemerataan antarwilayah untuk mengikis ketimpangan enclaving. Kedua, diversifikasi ekonomi melalui integrasi pertanian/perikanan ke rantai pariwisata. Ketiga, penguatan SDM dan pendidikan untuk menumbuhkan empathy dan mengatasi hambatan tradisional (traditional trap). Keempat, integrasi nilai modern-kearifan lokal agar modal sosial nagari mendorong partisipasi. Kelima, tata kelola berbasis partisipasi publik secara menyeluruh (from tradition to participation).
Dalam konteks teori Rostow dan Lerner, Pesisir Selatan membutuhkan kapasitas kelembagaan, sosial, dan ekonomi agar modernisasi tidak hanya menjadi slogan, melainkan transformasi substantif yang mampu menurunkan kemiskinan secara permanen, menjadikan Pesisir Selatan benar-benar menjadi “Negeri Sejuta Pesona” bagi seluruh penduduknya. (*)