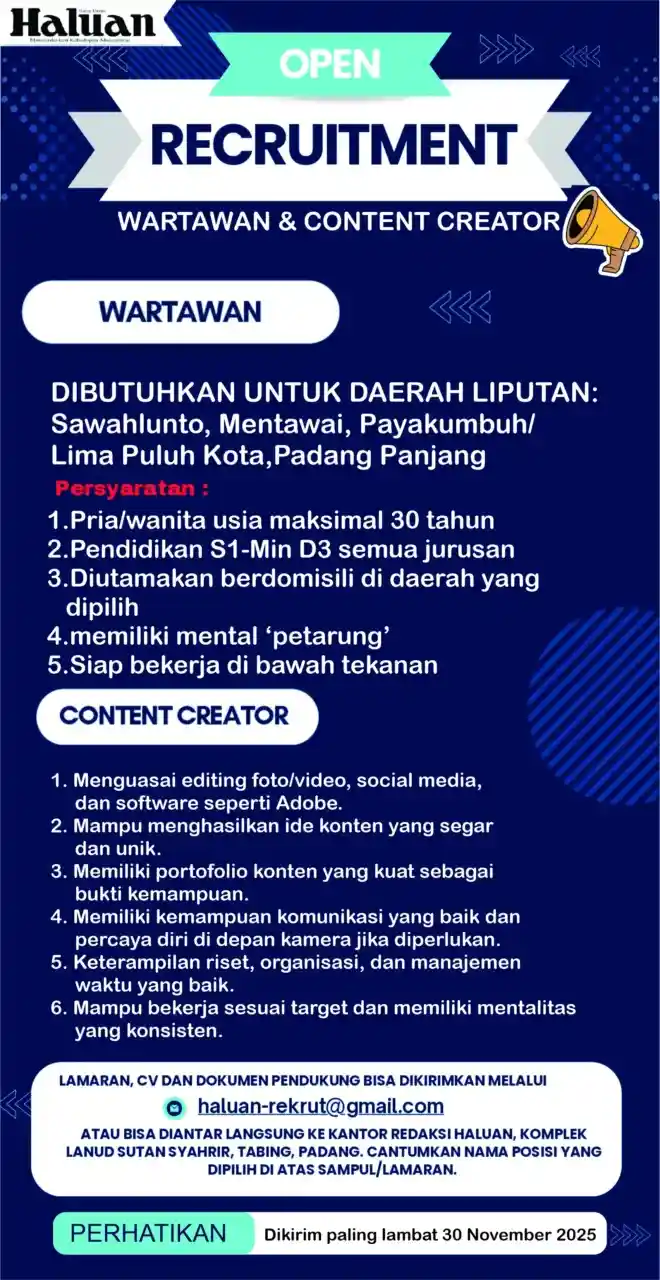Oleh: Annisa Adhilla, S.Psi
Fenomena pekerja seks komersial (PSK) atau wanita tunasusila (WTS) hingga kini masih menjadi salah satu persoalan sosial paling kompleks di Indonesia. Istilah “wanita tuna susila” sendiri merupakan istilah resmi yang diperkenalkan pemerintah melalui SK Menteri Sosial No. 23/HUK/96 sebagai bentuk eufemisme dari “pelacur”. Namun penggunaan istilah yang lebih halus tidak secara otomatis menghapus stigma dan persoalan yang menyertai dunia prostitusi.
Di balik gemerlap malam kota, prostitusi terus tumbuh sebagai realitas sosial yang sulit dikendalikan. Pada tahun 2006, tercatat sekitar 240 ribu perempuan bekerja dalam industri prostitusi, dan yang lebih memprihatinkan, 30 persen di antaranya adalah anak di bawah 18 tahun. Angka ini menggambarkan persoalan struktural yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan moralitas.
Kemiskinan sebagai Pendorong Utama
Beragam faktor dapat mendorong perempuan masuk ke dunia prostitusi, namun kajian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan alasan paling dominan. Penelitian Sejati (2024) di Bengkulu menemukan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja sebagai WTS melakukannya karena kesulitan ekonomi, konflik keluarga, dan pengalaman kekerasan.
Kemiskinan, minimnya pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja menjadi lingkaran yang menjerat banyak perempuan tanpa pilihan lain untuk mempertahankan hidup. Hasneli (2015) menegaskan bahwa krisis ekonomi turut memperluas kerentanan ini, terutama bagi perempuan tanpa keterampilan kerja.
Luka Psikologis yang Tidak Terlihat
Dampak psikologis yang dialami WTS sering kali tidak kasatmata, namun meninggalkan luka mendalam. Berbagai penelitian menggambarkan bagaimana stigma sosial membuat mereka merasa rendah diri, kehilangan motivasi, dan terjebak dalam perasaan tidak berdaya. Fenomena learned helplessness; perasaan bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah nasib, banyak ditemukan pada perempuan yang mengalami kekerasan dan berulang kali gagal keluar dari jeratan prostitusi.
Konsep diri yang negatif, kecemasan, dan tekanan emosional menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini semakin diperparah oleh cibiran, diskriminasi, dan penolakan masyarakat.
Stigma Sosial yang Mengunci Pintu Keluar
Stigma adalah tembok terbesar yang dihadapi WTS, baik saat masih aktif bekerja maupun ketika mencoba meninggalkan dunia tersebut. Masyarakat kerap memandang mereka sebagai “penyimpang moral”, “tidak bermoral”, atau “pembawa aib”. Pandangan ini membuat mereka terasing dan sulit diterima kembali dalam kehidupan sosial.
Tidak sedikit perempuan yang telah menjalani rehabilitasi akhirnya kembali ke prostitusi karena kesulitan mendapat pekerjaan layak atau tidak diterima lingkungan. Upaya keluar menjadi sia-sia ketika pintu-pintu sosial tertutup rapat.
Kehidupan Sosial dan Spiritual yang Kerap Terabaikan
Tak banyak yang menyadari bahwa para WTS tetap menjalankan kehidupan sosial dan spiritual sebagaimana masyarakat pada umumnya. Banyak dari mereka tetap menjalankan ibadah dan memegang nilai moral tertentu, meski harus berhadapan dengan dilema antara kebutuhan ekonomi dan ajaran agama. Konflik batin tersebut sering menjadi beban psikologis yang berat.
Untuk menghindari stigma, banyak WTS menyembunyikan profesinya dari keluarga atau tetangga. Strategi ini, walaupun melindungi mereka dari penolakan sosial, justru memperdalam tekanan emosional karena mereka harus terus menyembunyikan identitas.
Rehabilitasi yang Belum Menjawab Tantangan
Pemerintah telah menyediakan program rehabilitasi dan pembinaan melalui berbagai Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW). Program tersebut mencakup pembinaan fisik, mental, spiritual, sosial, serta pelatihan keterampilan.
Namun efektivitas program masih dipertanyakan. Durasi pembinaan yang umumnya hanya enam bulan dianggap terlalu singkat untuk memulihkan kondisi mental maupun membekali keterampilan yang memadai. Minimnya pendampingan pascarehabilitasi dan tidak tersedianya dukungan ekonomi membuat banyak perempuan kembali terjebak pada pekerjaan lama.
Padahal, penelitian menunjukkan bahwa dukungan social; baik dari keluarga maupun masyarakat; berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi WTS untuk memulai hidup baru.
Melihat Masalah Secara Lebih Manusiawi
Fenomena WTS tidak dapat diselesaikan hanya melalui razia atau penutupan lokalisasi. Kedua pendekatan tersebut terbukti belum menyentuh akar persoalan. Ketika lokalisasi ditutup tanpa strategi penguatan ekonomi, prostitusi justru berpindah ke ruang-ruang tersembunyi yang lebih sulit diawasi.
Kebijakan yang inkonsisten, stigma sosial yang mengakar, serta minimnya lapangan pekerjaan bagi perempuan adalah kendala utama yang harus diselesaikan.
Saatnya Pendekatan Holistik
Fenomena wanita tuna susila adalah gambaran nyata bahwa persoalan moral sering kali berakar dari persoalan struktural. Kemiskinan, ketimpangan, minimnya pendidikan, dan kekerasan menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dari pilihan-pilihan hidup yang tampak “menyimpang”.
Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan holistik:
a. Perbaikan kondisi ekonomi dan pendidikan perempuan,
b. Program pemberdayaan yang berkelanjutan,
c. Pendampingan psikologis yang memadai,
d. Kebijakan yang konsisten, serta
e. Pengurangan stigma melalui edukasi masyarakat.
Menghadapi fenomena WTS bukan hanya tentang menilai benar atau salah, tetapi tentang melihat manusia di balik profesi tersebut; perempuan yang berjuang dalam kondisi sulit dan membutuhkan ruang untuk kembali bermartabat. (*)