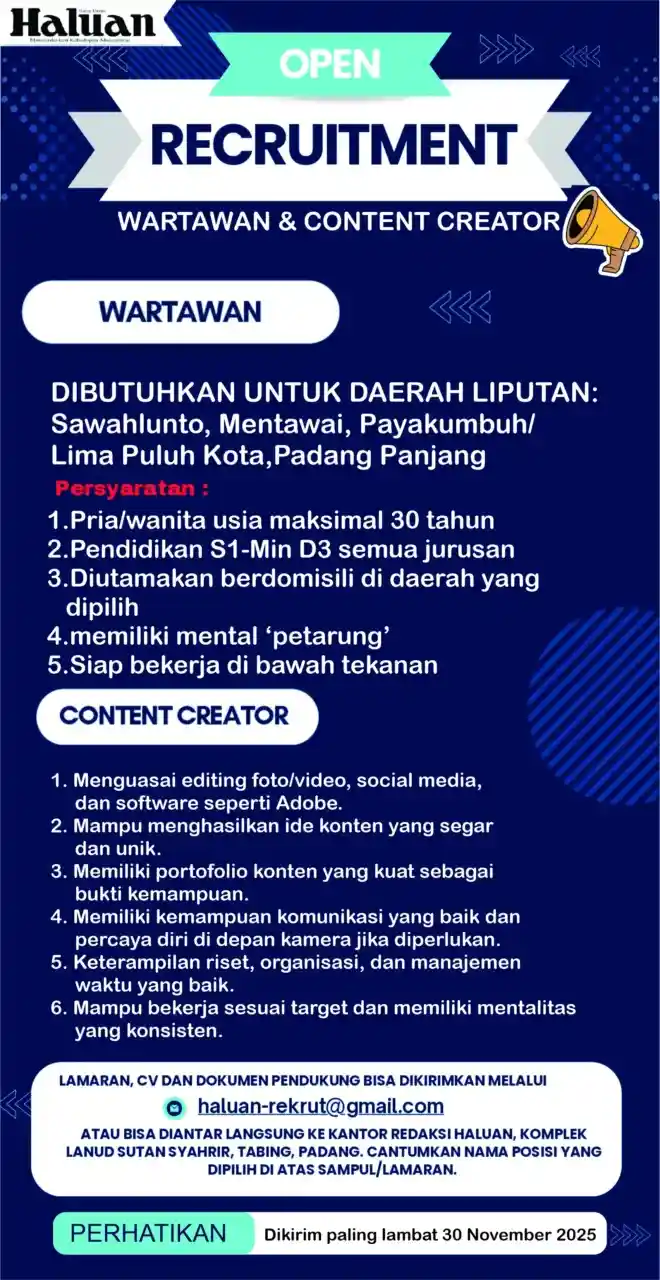Oleh: Muhammad Rasyid Ridho, S.Psi
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses belajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan berlangsung lewat platform digital yang menyediakan fleksibilitas tinggi dan akses informasi tanpa batas.
Namun dibalik kemudahan tersebut, muncul fenomena menurunnya motivasi belajar siswa. Banyak siswa merasa jenuh, kehilangan semangat, sulit fokus, dan mengalami kelelahan digital akibat paparan layar yang berkepanjangan.
Motivasi belajar yang seharusnya menjadi inti dari proses pendidikan justru meredup dalam lingkungan digital yang kompleks.
Untuk memahami akar persoalan ini, Self Determination Theory (SDT) dari Deci dan Ryan memberikan kerangka psikologis yang kuat dan relevan.
Ryan & Deci (2000) menjelaskan bahwa motivasi manusia akan tumbuh secara optimal ketika tiga kebutuhan psikologis dasar terpenuhi: autonomi, kompetensi, dan keterhubungan.
Dalam konteks pembelajaran digital, ketiga kebutuhan ini tidak selalu terpenuhi secara memadai. Akibatnya, siswa mengalami penurunan motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan strategi pembelajaran perlu berfokus pada pemenuhan kebutuhan psikologis tersebut agar motivasi kembali menyala.
Kebutuhan autonomi berkaitan dengan perasaan bahwa siswa memiliki kendali terhadap pilihan belajar mereka (Ryan & Deci, 2000).
Pembelajaran digital sebenarnya berpotensi besar untuk meningkatkan autonomi, karena siswa dapat menentukan waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Namun pada kenyataannya, banyak siswa justru merasa kewalahan oleh banyaknya tugas berbasis platform digital, deadline yang ketat, serta struktur pembelajaran yang kurang jelas.
Akibatnya, otonomi berubah menjadi tekanan. Dalam kerangka SDT, tekanan eksternal semacam ini menghambat motivasi intrinsik. Oleh karena itu, guru perlu memberikan ruang pilihan yang lebih fleksibel, seperti alternatif bentuk tugas, kebebasan memilih topik, atau penyesuaian cara belajar sesuai preferensi siswa.
Ketika autonomi dihargai, siswa akan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap proses belajarnya.
Kebutuhan kompetensi, yaitu merasa mampu dan efektif dalam menguasai tugas (Ryan & Deci, 2000), hal itu menjadi tantangan besar dalam pembelajaran digital. Siswa sering mengalami kesulitan memahami materi tanpa penjelasan langsung, serta merasa tidak kompeten saat menghadapi platform yang kompleks.
Ketika siswa berulang kali mengalami kegagalan atau kebingungan, motivasi mereka perlahan memudar. SDT menekankan bahwa umpan balik yang jelas, spesifik, dan mendukung sangat penting untuk membangun perasaan kompeten.
Guru perlu memastikan bahwa instruksi pembelajaran digital mudah dipahami, memberikan umpan balik segera (real time feedback), serta menyediakan contoh dan latihan yang mendukung.
Penggunaan elemen gamifikasi seperti level, badge, atau progress tracker dapat meningkatkan persepsi kompetensi jika digunakan secara tepat, bukan sebagai alat tekanan tetapi sebagai dukungan perkembangan.
Kebutuhan keterhubungan dengan lingkungan sekitar (Ryan & Deci, 2000), hal itu akan
semakin sulit terpenuhi ketika pembelajaran berlangsung secara virtual.
Interaksi tatap muka yang biasanya membangun rasa kebersamaan tergantikan oleh layar yang dingin dan komunikasi digital yang terbatas. Banyak siswa merasa terisolasi, jauh dari teman dan guru, serta kehilangan dukungan emosional yang biasanya diperoleh di kelas.
Dalam perspektif SDT, hilangnya keterhubungan menjadi salah satu faktor utama menurunnya motivasi.
Oleh karena itu, guru perlu menciptakan ruang interaksi sosial yang hangat meskipun berbasis digital.
Aktivitas diskusi kelompok, kolaborasi proyek, serta komunikasi personal melalui pesan atau umpan balik dapat membangun kembali rasa kedekatan.
Ketika siswa merasa dilihat, didengar, dan dihargai, motivasi mereka cenderung meningkat.
Dengan demikian, Self Determination Theory memberikan penjelasan yang mendalam
mengenai mengapa motivasi belajar siswa dapat padam dalam lingkungan digital.
Motivasi tidak sekadar bergantung pada teknologi, tetapi pada sejauh mana kebutuhan psikologis siswa terpenuhi.
Strategi untuk menyalakan kembali motivasi belajar tidak cukup hanya dengan menambah fitur digital yang menarik, tetapi harus menyentuh aspek psikologis yang lebih mendasar.
Ketika autonomi dihargai, kompetensi didukung, dan keterhubungan diperkuat,
digitalisasi pendidikan bukan lagi ancaman bagi motivasi belajar, melainkan menjadi peluang untuk membangun pengalaman belajar yang lebih bermakna.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan bagaimana dunia pendidikan mampu merancang proses pembelajaran digital yang memanusiakan siswa.
Dengan memahami prinsip-prinsip SDT, guru, sekolah, dan pengembang platform belajar dapat merancang strategi psikologis yang efektif untuk menghidupkan kembali semangat belajar yang sempat meredup.
Pembelajaran digital dapat menjadi ruang yang penuh motivasi ketika kebutuhan psikologis siswa diakui dan dipenuhi secara konsisten. (*)