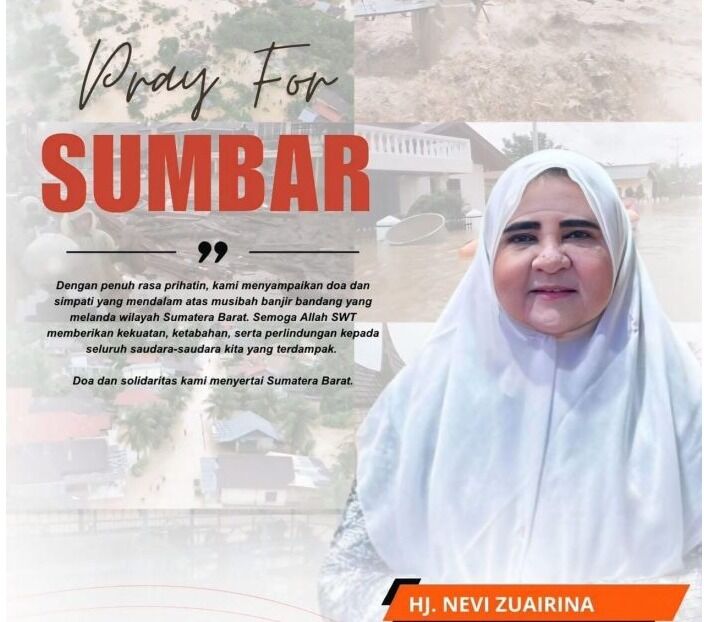Oleh: Okis Mardiansyah
Wartawan Haluan Kabupaten Pesisir Selatan
Hujan turun sore itu. Mula-mula pelan, seperti biasa. Gemericik yang biasanya menenangkan kini terdengar mencemaskan. Di balik jendela, air yang semula mengalir kecil di halaman rumah berubah menjadi aliran yang merayap, lalu meluas tanpa izin. Jalan depan rumah lenyap ditelan air cokelat kekuningan, dan suara-suara panik mulai terdengar. Perabotan rumah tangga diangkat ke tempat yang lebih tinggi, anak-anak hingga orang dewasa bergegas mencari tempat berlindung. Warga berteriak satu sama lain, “Air sudah masuk!”
Adegan seperti ini telah berulangkali terjadi. Setiap musim hujan datang, kita seperti menunggu sebuah film yang tak pernah berganti judul. Sebagian menyebutnya malapetaka cuaca, alam sedang murka, sebagian lagi menyalahkan sungai yang “tak lagi bersahabat dengan kita”. Namun, jarang ada yang berani menatap cermin, sebab banjir bukan sekadar hujan yang jatuh, tetapi hasil dari tangan manusia yang rakus.
Dulu, hutan kita bukan sekadar kumpulan pepohonan. Ia adalah penopang kehidupan. Ketika hujan menimpa daun, air tertahan, disaring, lalu perlahan turun ke tanah. Akar-akar menjalin diri seperti jemari ibu yang menenangkan anaknya. Sungai tidak pernah marah, karena ia diberi kesempatan bernapas. Air berjalan sesuai jalur alami, tenang, terukur, dan penuh perhitungan.
Namun kemudian datang manusia dengan gergaji dan kepentingannya. Pohon ditebang bukan karena kebutuhannya, tetapi karena keinginannya. Satu batang tumbang, lalu dua, lalu puluhan, lalu ratusan. Di tebing-tebing yang dulu hijau, kini tersisa guratan tanah yang telanjang. Bukit yang dulu terasa tinggi dan gagah kini tampak bergetar dalam sunyi. Tidak lagi ada akar yang memeluknya, tidak ada daun yang menahan hujan, tidak ada batang yang menjadi penyangga. Hutan menjadi luka, dan luka alam tak pernah menunggu lama untuk memberi balasan.
Kita sering mendengar alasan klasik, bahwa kayu itu rezeki, pembangunan butuh bahan baku. Betul, kita butuh hidup. Tetapi pertanyaannya, kehidupan siapa yang kita jaga? Orang yang menebang mungkin mendapatkan uang sekejap, pedagang kayu mungkin membeli motor atau membangun rumah. Tapi ketika rumah-rumah lain tenggelam oleh banjir, siapa yang menanggung kerugian? Saat sawah terendam lumpur dan gagal panen, kepada siapa petani mengadu? Ketika sekolah-sekolah tak bisa digunakan karena air setinggi pinggang, siapa yang kehilangan masa depan?
Alam sesungguhnya tidak pernah kejam. Ia hanya balas berperilaku sesuai perlakuan yang diterimanya. Kita menebang pohonnya, ia melepaskan airnya. Kita merusak akar, ia meluapkan sungainya. Kita memperlakukan alam sebagai benda mati, ia menunjukkan bahwa ia hidup, dan ia menyimpan ingatan.
Yang paling menyedihkan adalah bagaimana bencana mengikis bukan saja harta benda, tetapi rasa memiliki. Setiap banjir datang, sebagian warga memilih pergi. Ada yang meninggalkan kampung halamannya, ada yang enggan berinvestasi, ada yang kehilangan kepercayaan pada tanah yang dulu ia cintai. Banjir tidak hanya merusak lingkungan, ia merusak hubungan kita dengan tempat asal. Itu adalah kehilangan yang tak bisa dinilai dengan angka rupiah sekalipun.
Kita membutuhkan keberanian moral, keberanian untuk berkata bahwa pohon bukan sekadar kayu yang bisa dijual, melainkan kehidupan yang dilindungi. Kita membutuhkan pemerintah yang tidak hanya hadir setelah air surut, tetapi bekerja sebelum malapetaka datang. Kita memerlukan hukum yang bukan sekadar pasal di atas kertas, tetapi senjata yang melindungi hutan dari para pemburu keuntungan jangka pendek.
Namun semua itu tidak cukup tanpa perubahan di hati kita. Seorang anak kecil mungkin tak pernah tahu arti deforestasi, tapi ia tahu apa rasanya bermain di lapangan yang tergenang air banjir. Seorang ibu mungkin tidak mengerti istilah “resapan tanah”, tapi ia mengerti pedihnya mengeringkan kasur basah sambil menenangkan anaknya. Dan sebagian orang tua mungkin tak paham teori hidrologi, tapi ia mengerti bahwa hutan yang hilang membuat kampungnya tak lagi nyaman ditempati.
Banjir bukan sekadar air yang datang dari langit. Ia adalah sungai yang menangis karena kehilangan pelindungnya. Ia adalah tanah yang melepaskan sakitnya pada permukaan. Ia adalah alam yang mencoba berbicara dengan bahasa yang paling keras agar kita mendengar.
Selama kita masih memandang pohon hanya sebagai balok yang bisa ditebang, banjir akan selalu menggenang di halaman rumah kita. Dan selama kita menunggu seseorang untuk menanam pohon pertama, tidak ada keajaiban yang akan datang.
Jangan lagi menunggu banjir berikutnya untuk bertindak. Tanamlah satu pohon hari ini. Peluklah hutan yang tersisa. Karena kayu boleh ditebang sekali, tetapi banjir bisa kembali berkali-kali. Dan jika kita tidak berbuat apa-apa, air bukan hanya menggenang, ia akan menghapus jejak masa depan kita. Wallahu a’lam. (*)