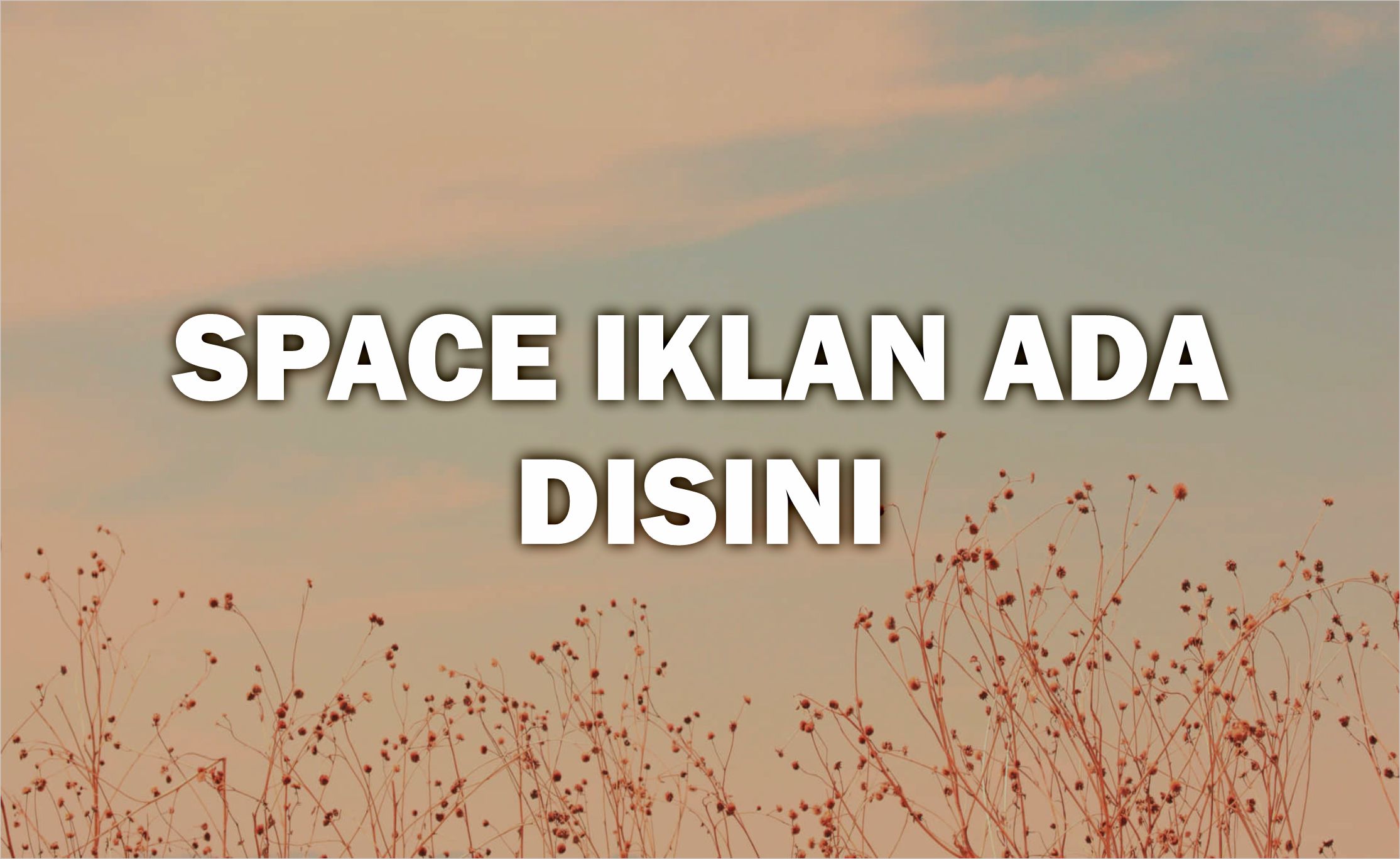Oleh: Muhammad Nazri Janra (Departemen Biologi Fakultas MIPA Unand)
Sebagai orang yang pernah tinggal selama nyaris lima tahun di Negeri Paman Sam untuk melanjutkan pendidikan, serta menyinggahi beberapa negera lainnya dalam kurun waktu yang sama untuk kepentingan akademis, tentunya sedikit banyak bisa terlihat bagaimana kondisi hidup di masing-masing tempat. Untuk negara maju seperti Amerika Serikat, yang melandasi status kewarganegaraannya berdasarkan kelahiran di tanah Amerika (Amandemen ke-14 Konstitusi AS) dan proses naturalisasi, banyak fasilitas yang menjamin kenyamanan hidup warganya.
Bahkan fasilitas ini juga diperluas kepada para pendatang yang masih berstatus imigran legal, mengingat adanya aturan kewarganegaraan berdasarkan aturan naturalisasi yang disebutkan di dalam konstitusi mereka. Sehingga jika seseorang dari negara dunia ketiga seperti Indonesia menjadi pendatang legal di negara tersebut (dan juga negara-negara maju lainnya), bisa dipastikan terasa perbedaan taraf hidup yang sangat signifikan dengan negara asal.
Selain alasan kelayakan hidup tadi, mengejar tingkat pendidikan yang lebih baik dengan banyaknya lembaga pendidikan bertaraf global di negara-negara maju tersebut serta pekerjaan dengan upah yang tinggi juga menjadi faktor penarik bagi mereka yang jamak dikenal dengan istilah “diaspora” tersebut. Banyak yang menganggap bahwa motivasi diaspora yang menjadi pekerja migran tersebut semata untuk kesejahteraan pribadi.
Memang tidak bisa ditampik jika bayaran dan kesejahteraan yang lebih tinggi menjadi faktor pemicu utama, ditambah dengan perbedaan harga tukar mata uang antarnegara tempat bekerja dengan rupiah membuat gaji para diaspora ini benar-benar “terasa”. Perbedaan kurs ini yang sangat mungkin menjadikan para diaspora pekerja atau pekerja migran Indonesia (PMI) ini tercatat sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah ekspor minyak dan gas dengan catatan angka sebesar USD14,2 miliar atau Rp227 triliun pada tahun 2024 yang baru lalu. Ini tentu jumlah fantastis yang tidak sedikit dalam peranannya menjadi penyokong pembangunan negara.
Lalu ketika ada oknum pejabat yang kebetulan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil bernyanyi sumbang dengan menyangsikan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para diaspora tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai banyaknya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan beralih kewarganegaraan. Sebenarnya pernyataan ini tidak mengejutkan keluar dari seorang Bahlil, yang walaupun menjabat sebagai seorang menteri, tetapi memiliki track record “malprestasi” yang membuat banyak dari kita bertanya-tanya kenapa masih dipertahankan sebagai seorang pejabat publik. Terakhir kebijakan yang ditelurkannya mengenai pelarangan distribusi gas ukuran 3 kilogram di luar agen resmi menyebabkan jutaan rakyat terpaksa antre panjang dan menelan korban dua korban jiwa. Untung saja, katanya, kebijakan ini kemudian dibatalkan.
Dalam tulisan ini mungkin kita tidak akan membahas pernyataan dari oknum menteri tersebut. Tetapi lebih menitikberatkan kepada para diaspora asal Indonesia dan peranannya terhadap negara tercinta ini. Mungkin karena secara fisik para diaspora tersebut tidak berada di negara asalnya yang seringkali menjadikan banyak pihak meragukan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia yang telah ditinggalkannya.