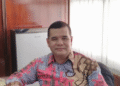HARIANHALUAN.ID – Generasi Muda dan krisis harapan generasi muda kerap didaulat sebagai agent of change, pilar utama dalam mendinamisasi inovasi, memperkokoh demokrasi, serta membangun ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi pergeseran orien tasi eksistensial di kalangan pemuda Indonesia sebuah krisis harapan yang berujung pada eskapisme struktural ke luar negeri.
Fenomena ini terefleksikan dalam tagar #KaburAjaDulu, sebuah representasi kolektif dari keinginan gene rasi muda untuk mencari suaka masa depan yang lebih prospektif di negeri orang.
Fenomena migrasi ini dapat dielaborasi melalui theory of push and pull factors yang dikemukakan oleh Everett Lee. Dalam teorinya, Lee menegaskan bahwa perpindahan penduduk bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan dipicu oleh faktor pendorong (push factors) dari negara asal, seperti instabilitas ekonomi, ketimpangan sosial, serta ketidakpastian politik, yang kemudian dikontraskan dengan faktor penarik (pull factors) dari negara tujuan, seperti peluang kerja yang lebih luas, sistem kesejahteraan yang komprehensif, serta ekosistem profesional yang lebih meritokratis.
Tidak mengherankan jika negaranegara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Jerman, dsb menjadi magnet bagi kalangan muda berkompetensi tinggi dari Indonesia.
Dari Optimisme ke Pesimisme
Fenomena ini tidak dapat dipandang secara ahistoris. Dalam kajian sosiologi historis, migrasi generasi muda dapat dipahami melalui social pendulum theory yang menggambarkan bagaimana ekspektasi kolektif terhadap negara mereka berayun dalam siklus optimisme dan pesimisme.
Ketika negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas politik yang terjaga, generasi muda cenderung menaruh kepercayaan terhadap masa depan mereka di tanah air. Namun, saat stagnasi ekonomi melanda, ketimpangan sosial semakin melebar dan institusi demokrasi mengalami erosi, maka pesimisme pun menguat, mendorong gelombang emigrasi yang masif.
Pitirim Sorokin, dalam teorinya tentang social mobility, menegaskan bahwa individu akan senantiasa mencari jalur mobilitas alternatif ketika struktur sosial-ekonomi yang ada gagal menyediakan ruang bagi aktualisasi diri dan kesejahteraan mereka.
Realita Pasar Kerja: Pendidikan Tinggi, Gaji Rendah
Salah satu paradoks fundamental yang dihadapi generasi muda Indonesia adalah ketimpangan antara kualifikasi akademik dan realitas pasar kerja. Michael Spence, melalui job market signaling theory, menegaskan bahwa gelar akademik tidak selalu menjadi indikator absolut bagi akses terhadap pekerjaan yang layak, terutama dalam konteks pasar tenaga kerja yang mengalami oversaturasi (jumlah pekerja yang tersedia di pasar tenaga kerja melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia).