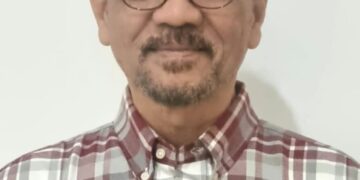Oleh:
ABDUL AZIZ
Mahasiswa Program Doktor Manajemen
Universitas Andalas
Sesungguhnya apa yang tertuang dalam tulisan berjudul “Semen Indonesia: Turnaround atau Mati” di Kompasiana.com tanggal 22 Mei 2025 telah lama menjadi rintihan para karyawan PT Semen Padang serta pemerintah daerah Sumatera Barat. Namun, tidak jelas kemana seharusnya saluran aspirasi ini disampaikan. Suara kegelisahan yang mencerminkan penurunan peran dan fungsi strategis Semen Padang telah menjadi gema sunyi yang tertahan di balik narasi besar konsolidasi BUMN. Padahal, sejak awal transformasi PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., berbagai pihak telah mengkhawatirkan bahwa integrasi tersebut berpotensi mengikis daya saing anak perusahaan yang telah memiliki pasar dan identitas kuat, sebagaimana halnya Semen Padang di Sumatera dan sekitarnya.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., sebagai BUMN strategis dan pemimpin pasar semen nasional, seharusnya memosisikan diri bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan. Ketika perusahaan ini memutuskan untuk melakukan konsolidasi merek dan strategi distribusi secara terpusat, seharusnya pendekatan yang digunakan memperhatikan keunggulan lokal dan potensi diferensiasi dari masing-masing anak perusahaan. Dalam konteks manajemen strategis, pendekatan resource-based view (Barney, 1991) menegaskan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan lahir dari pemanfaatan sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Semen Padang memiliki semua elemen itu: sejarah yang panjang sejak 1910, loyalitas pelanggan di wilayah barat Indonesia, sumber daya manusia lokal yang berpengalaman, serta jaringan distribusi yang telah terbukti efektif.
Namun, dalam realitas manajerial yang diterapkan induk perusahaan, diferensiasi ini seolah-olah dipangkas dan digantikan oleh logika integrasi pusat yang terlalu berbasis efisiensi struktural jangka pendek. Padahal menurut Porter (1985), strategi korporasi yang berhasil adalah yang mampu menggabungkan efisiensi biaya dan diferensiasi berbasis nilai tambah lokal. Ketika seluruh pengelolaan pasar dan harga ditarik ke pusat, maka entitas seperti Semen Padang kehilangan daya tawar, kehilangan kontrol terhadap wilayah pemasarannya sendiri, dan akhirnya kehilangan kapasitas produksi secara drastis. Situasi ini mengindikasikan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip strategis berbasis konteks.
Manajemen PT Semen Indonesia seharusnya menempuh strategi pemasaran yang tidak seragam tetapi localized differentiation, di mana kekuatan merek dan sejarah Semen Padang bisa tetap hidup dan menjadi instrumen daya saing regional. Dalam dunia bisnis modern yang hiperkompetitif, merek lokal yang kuat adalah aset, bukan beban. Mengeliminasi kekuatan merek tersebut demi homogenisasi adalah bentuk pengingkaran terhadap realitas pasar yang majemuk.
Dampak dari pendekatan tersebut bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Penurunan produksi dan penjualan Semen Padang berarti penurunan aktivitas ekonomi lokal, berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), dan terganggunya program pembangunan. Data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2023) menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur, tempat Semen Padang berperan besar, menyusut kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 7% dalam dua tahun terakhir. Kontraksi ini tidak bisa dilepaskan dari berkurangnya aktivitas produksi Semen Padang yang dahulu menjadi tulang punggung ekonomi Sumbar.
Pemerintah Daerah Sumatera Barat, melalui jalur resmi dan diplomasi kebijakan, semestinya menyampaikan keprihatinan dan keberatan ini kepada Kementerian BUMN sebagai pembina korporasi milik negara. Dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, otonomi daerah memberikan kewenangan dan legitimasi kepada pemerintah provinsi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakatnya. Jika Semen Padang terus diperlakukan sebagai sekadar unit produksi tanpa kemandirian strategis, maka Sumatera Barat kehilangan lebih dari sekadar perusahaan: ia kehilangan identitas industrial yang telah dibangun selama lebih dari satu abad.
Dalam literatur tentang strategic corporate governance, relasi antara BUMN dan pemerintah daerah semestinya tidak bersifat hirarkis satu arah, tetapi kolaboratif dalam semangat co-creation of value (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Pemerintah daerah bisa dan harus memainkan peran sebagai mitra strategis, yang tidak hanya menyuarakan kritik tetapi juga menawarkan solusi. Salah satunya adalah mendorong pemulihan strategi penjualan dan distribusi Semen Padang secara mandiri, dengan supervisi pemerintah pusat, namun memberi ruang gerak yang cukup bagi unit lokal untuk mengelola keunikan pasarnya.
Sumatera Barat, sebagai salah satu pusat lahirnya ide dan praktik demokrasi di Indonesia, memiliki posisi moral dan historis yang kuat untuk melobi pemerintah pusat. Tidak ada salahnya menginisiasi dialog terbuka, diskusi strategis dengan Kementerian BUMN, bahkan mengusulkan restructuring internal yang memberikan kembali mandat kemandirian pemasaran bagi Semen Padang. Karena selain memiliki kapasitas produksi yang mumpuni, kualitas semen yang dihasilkan oleh Semen Padang tidak kalah dengan pabrik manapun di Indonesia. Dalam beberapa riset kualitas produk semen nasional, produk dari pabrik di Indarung justru menunjukkan konsistensi dalam standar mutu dan ketahanan struktur (Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PUPR, 2022).
Jika pendekatan integratif yang bersifat sentralistis terus dipertahankan, tanpa adanya ruang adaptasi lokal, maka yang terjadi bukan hanya penurunan kinerja anak perusahaan, melainkan juga erosi kepercayaan terhadap niat awal pendirian holding. Padahal niat tersebut mulia: menciptakan sinergi antar perusahaan semen nasional agar mampu bersaing di kawasan ASEAN. Namun dalam praktiknya, sinergi itu justru meniadakan otonomi strategis yang semestinya dijaga.
Dari perspektif manajemen strategis kontemporer, korporasi publik yang sehat adalah yang mampu menyeimbangkan tiga elemen: efisiensi organisasi, adaptasi terhadap pasar lokal, dan penciptaan nilai sosial (shared value). Model seperti ini diperkenalkan oleh Porter & Kramer (2011) yang menekankan pentingnya perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Dengan kata lain, Semen Indonesia tidak bisa hanya berpikir sebagai produsen semen; ia harus menjadi katalis pembangunan lokal, yang dalam hal ini, termasuk menjamin keberlangsungan Semen Padang sebagai entitas bernilai strategis.
Kita tidak menolak konsolidasi. Kita tidak menolak modernisasi. Tetapi kita menolak perlakuan yang mengorbankan entitas lokal dengan sejarah panjang dan kontribusi besar, hanya demi sebuah efisiensi korporasi yang sempit. Keseimbangan antara struktur holding dan kemandirian strategis anak perusahaan adalah kunci keberhasilan jangka panjang BUMN di sektor strategis.
Semoga suara yang selama ini hanya bergema dalam sunyi, kini menemukan ruang yang lebih terang. Suara yang tidak hanya berasal dari pekerja Semen Padang atau pejabat daerah, tetapi juga dari rakyat Sumatera Barat yang merasa kehilangan sesuatu yang telah menjadi bagian dari identitas mereka selama lebih dari seratus tahun. (*)