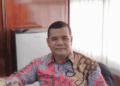Dengan demikian, luas areal tanam efektif akan hilang akibat kanalisasi sekitar 1,53 ton/ha {(2.250m2:10.000 m2)×6,8 t/ha}. Artinya, produksi riil SPM bukan rata-rata 6,8 ton/ha (survei Field di 53 lokasi), akan tetapi menjadi sekitar 5,3 t/ha. Angka produksi ini saya sebut sebagai dampak negatif SPM-1.
Persoalan kehilangan areal tanam efektif ini mesti kita refleksikan pada masalah sudah semakin terbatasnya lahan bukaan baru untuk sawah di Indonesia. Kalaupun ada, sebagian besar marginal, baik dari sisi biofisik, infrastruktur, dan sosial.
Saya sering menonton teknologi SPM ini di postingan Ir. Djoni di Facebook. Apabila diperhatikan lebih teliti, maka jarak tanam SPM itu berkisar antara 35×25 cm, karena hanya 4 rumpun tanaman dalam lebar gludan 1,25 m. Padahal kalau jarak tanamnya 25×25 cm, untuk lebar 1 meter saja mestinya terdapat 5 rumpun tanaman, apalagi rumpun tanaman bagian kiri dan kanan sudah sangat dekat ke tepi bedengan.
Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan jarak tanam 25×25 cm (160.000 rumpun/ha) atau 124.000 rumpun per total luas bedeng (775.000 m2), maka dengan jarak tanam 35×25 cm ini, akan hilang lagi sekitar 46.000 rumpun tanam, artinya berkurang hasil sekitar 28,8 persen (1,52 ton/total luas gludan).
Kalau opsi jarak tanamnya 25×25 cm, sementara lebar bedengan 1,25 cm hanya ditempati oleh 4 baris tanaman, maka areal efektif tanam yang akan hilang lebih besar lagi, sehingga saya tak berani meneruskan hitung-hitungan ini. Pengaruh jarak tanam ini saya sebut sebagai dampak negatif SPM-2.
Kedua dampak negatif SPM terhadap produksi riil cukup luar biasa, marilah kita coba menghitung ulang bersama. Bagi saya, anggap saja, potensi pengurangannya separuh dari perhitungan ini, maka SPM sepertinya tetap saja menyandang prediket “bermodal murah-berproduksi riil rendah”.