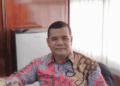Perhitungan sederhana dan aktual yang sedikit rumit ini sengaja saya kemukakan, agar kita lebih realistis melihat SPM ini dari perspektif ketahanan pangan nasional, yang pendekatannya produktivitas tinggi dan produksi riil tidak boleh berkurang karena pendekatan teknologi. Apalagi visi Indonesia tidak hanya keberlanjutannya Swasembada Pangan Nasional, akan tetapi juga menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045.
Keempat, teknologi SPM tidak serta merta bisa disimpulkan murah, kalau diperhitungkan biaya memisahkan jerami ke tempat tertentu, pemotongan tunggul padi sehingga rata dengan permukaan tanah, pembuatan kanal seluas 2.400 m2/ha, pembuatan bedengan, mencencang jerami, kemudian menyusun jerami diatas bedengan, termasuk pengaturan tata air di kanal agar bedengan tidak terendam. Artinya, teknologi SPM bisa dikategorikan masih labor intensive, sementara tenaga kerja tani semakin terbatas sebagai akibat laju urbanisasi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga biaya upah menjadi tinggi. Di samping itu, karena petani yang memiliki lahan sempit (0,1–0,3 ha) mencapai 57,2 persen di Indonesia, yang terpaksa memicu petani mencukupi kebutuhan hidupnya di sektor off farm, maka semakin memaksa kita untuk lebih cermat mempromosikan SPM ini dalam budidaya padi sawah, baik lokal
maupun nasional.
Kelima, menurut hemat saya teknologi SPM masih menyisakan banyak pertanyaan dari beragam aspek keilmuan, seperti kenapa jarak antar bedengan sangat intensif (1,25 m); berapa cepat hara tersedia dalam kondisi jerami tanpa fermentasi serta seberapa mampu jerami menyediakan kecukupan hara sepanjang siklus hidup tanaman padi; secara teoritis pemberian bahan organik atau jerami lebih efektif menyediakan hara apabila dibenamkan sebelum pengolahan tanah, sementara penggenangan sawah pada prinsipnya adalah untuk mengendalikan gulma. Dalam konteks SPM, penebaran jerami dimaksudkan untuk mengendalikan gulma. Nah, opsi mana yang lebih menguntungkan dari sisi produktivitas padi: dibenamkan atau ditebar dalam kondisi dihamparkan? Lalu, jerami sudah terurai 30–40 hari setelah ditebar, apakah masih efektif mengendalikan gulma pada stadium selanjutnya, sementara bedengan dikondisikan tidak tergenang, yang biasanya akan mendorong aktifnya pertumbuhan gulma.
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa 1) SPM sebagai teknologi yang cenderung menghindari pemakaian agro input sebenarnya identik dengan teknologi tradisional, sehingga sebenarnya kurang cocok dengan penggunaan varietas unggul yang relatif rakus pupuk; 2) SPM murah dari aspek tanpa penggunaan agro input, akan tetapi menjadi mahal sebagai akibat relatif masih labor intensive, sehingga kurang cocok dalam kondisi Indonesia, yang semakin terbatas kesediaan tenaga kerjanya sebagai akibat laju urbanisasinya tinggi; dan 3) SPM yang produksi riilnya sangat rendah sebagai akibat mengurangi luas lahan efektif yang ditanami sebagai akibat amat intensifnya kanalisasi, serta pengurangan jumlah rumpun tanam akibat pembuatan bedeng selebar 1,25 m, maka sangat tidak memenuhi azas dan visi keberlanjutan Swasembada Pangan Nasional dan Lumbung Pangan Dunia 2045. (*)