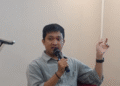Keterpinggiran Bahasa, Awal Pemicu Krisis Identitas
Kini di Ranah Minangkabau, ajaran adat dan budaya sudah terpinggirkan dan dianggap tidak penting. Ia tidak lagi masuk ke dalam sistem pendidikan baik formal maupun informal sebagai proses pewarisan. Membuat generasi muda semakin jauh dari adat budayanya. Sekarang mereka lebih akrab dengan budaya pop dan gaya hidup moderen, tanpa memahami sejarah dan nilai-nilai budaya yang ada, semisal dalam tambo, pepatah petitih, atau sistem kekerabatan Minang yang matrilineal.
Lebih parahnya lagi, bahasa Minangkabau sebagai bahagian dari aspek budaya yang sangat penting dalam upaya mempertahankan identitas (jati diri) – karena bahasa menunjukkan bangsa/kaum – kini secara perlahan ditinggalkan oleh kebanyakan para orang tua. Di rumah dengan anak-anak, mereka berbahasa Indonesia karena merasa lebih “keren & moderen”, bahasa Minangkabau dianggap kasar dan kuno.
Sekarang mari kita lihat beberapa pernyataan pakar bahasa dunia, dan mengapa Barat begitu sangat peduli dengan bahasa. Lemkin (1944) penemu istilah genosida, mendefinisikan bahwa genosida tidak hanya sebagai pembunuhan fisik, tetapi juga penghancuran struktur sosial, budaya dan agama. Ia menegaskan, genosida bahasa adalah unsur utama dalam membunuh ‘jiwa’ suatu bangsa atau etnik. Selanjutnya Kangas (2000) mengembangkan istilah linguicide (penghancuran bahasa) adalah membunuh suatu etnik atau bangsa tanpa senjata.
Karena, ketika suatu kelompok kehilangan bahasanya, maka mereka akan turut kehilangan kemampuan untuk mengenal dan melanjutkan eksistensinya sebagai suatu kelompok yang berbeda. Sementara itu, Ngugi (1986) menyatakan, bahasa kolonial (Inggris dan lain-lainnya) adalah “bom budaya” yang menghancurkan ingatan kolektif, identitas dan keyakinan diri masyarakat pribumi. Sedangkan di satu sisi, bahasa adalah inti perlawanan kepada kolonialisme, sekaligus alat pemulihan budaya.
Ketika saya menghadiri Konferensi Bahasa Daerah pada 2016 di Bandung, Salah seorang peserta asing memaparkan hasil penelitiannya, yang membuat saya kaget, bahwa salah satu dari 25 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah karena ditinggalkan oleh penurutnya adalah bahasa Minangkabau. Lalu, jika demikian, apa yang akan terjadi dengan Minangkabau ke depan, yang kini sedang menghadapi krisis identitas?
ABS-SBK dalam Krisis Pewarisan
Zaman dulu, pewarisan adat Minangkabau – yang kaya akan nilai demokrasi, musyawarah, etika sosial, dan relasi egaliter antara perempuan dan laki-laki – kini telah kehilangan tempatnya dalam pendidikan formal maupun non-formal. Kalau pun ada, tapi sifatnya tidak menyeluruh dan tidak sistemik. Buku pelajaran sekarang tidak lagi memuat BAM (Budaya Alam Minangkabau), dan guru-guru tidak ada lagi yang memiliki kompetensi mumpuni untuk mentransmisikan nilai-nilai ABS-SBK tersebut secara kontekstual.
Menurut Afrilya, Siregar & Jubaedah (2020), kearifan lokal Minangkabau kini semakin tersingkir dari dunia pendidikan, karena tidak lagi dianggap relevan oleh kurikulum nasional yang terlalu terpusat. Akibatnya, generasi muda tidak mengenal nilai, tidak bangga dengan identitasnya, sementara mereka sangat terbuka dan rentan terhadap budaya luar yang masuk tanpa ada filter. Ini membuat generasi Minangkabau makin menjauh dari prilaku adat budayanya.
Setelah pelajaran BAM dihilangkan pada 2013, anak-anak sekarang tidak lagi memahami sejarah dan adat budayanya. Rasa cinta mereka terhadap Minangkabau menipis, dan cenderung melihat Minangkabau dari sisi kekurangannya. Hal ini akan membuat mereka kehilangan jati diri (lost identity), dan pada saatnya nanti dapat megancam keutuhan dan persatuan masyarakat. Karena pengaruh ideologi lain akan mudah masuk, memecah belah dan merusak tatanan kehidupan Minangkabau yang sudah terbina selama ini.




![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 2]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-Kini-120x86.jpg)
![Minangkabau Kini: ABS-SBK Tinggal Semboyan, Agama Hanya Simbol dan Ritual [Bagian 1]](https://harianhaluan.id/wp-content/uploads/2025/08/REFLEKSI-Minangkabau-120x86.jpg)