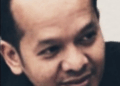Sementara itu, kemajuan teknologi dan otomasi memperdalam dilema pasar kerja. Banyak perusahaan mengganti pekerja berupah rendah dengan mesin atau sistem digital. Carl Benedikt Frey dalam The Technology Trap (2019) menggambarkan bagaimana gelombang otomasi selalu menciptakan pemenang dan pecundang, produktivitas meningkat, tetapi kesempatan kerja menurun jika adaptasi sosial dan kebijakan publik tertinggal. Indonesia berisiko terperangkap dalam “jebakan teknologi” ini, terlalu cepat beralih ke otomasi, namun tanpa strategi pelatihan ulang yang memadai bagi pekerja yang terdampak.
Faktor eksternal lain juga memperburuk keadaan. Arus impor barang konsumsi dan bahan baku meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir, menggerus daya saing industri dalam negeri. Banyak industri kecil menengah sulit bertahan menghadapi barang impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Ketika pabrik tutup, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor informal. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan produktivitas nasional dan memperlebar jurang sosial.
Selain itu, kebijakan sumber daya manusia Indonesia juga masih belum mampu menjawab tantangan struktural pasar tenaga kerja. Program pendidikan vokasi belum terhubung erat dengan kebutuhan industri. Lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur, sementara perusahaan mengeluh kekurangan tenaga terampil di bidang teknis, manufaktur, dan teknologi informasi. Ketidaksesuaian ini menciptakan mismatch antara permintaan dan pasokan tenaga kerja, lalu memperlambat proses industrialisasi.
Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi gagal memanfaatkan bonus demografi yang kini sedang berlangsung. Sekitar 70 persen penduduk berusia produktif, dan puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2035. Namun, tanpa pertumbuhan lapangan kerja yang sepadan, jumlah pengangguran dan setengah pengangguran akan meningkat. Generasi muda terancam hanya bekerja di sektor informal, atau terjebak dalam pekerjaan sementara di ekonomi digital tanpa jaminan sosial. Fenomena ini sudah terlihat pada maraknya pekerja platform seperti pengemudi daring, kurir, dan pekerja lepas yang berada di wilayah abu-abu antara kemandirian dan eksploitasi.
Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah “ledakan demografi terbalik”, jumlah usia produktif besar, tetapi tidak terserap dengan baik, sehingga menekan produktivitas dan meningkatkan beban sosial negara. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu kekecewaan sosial, ketegangan politik, dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi.
Untuk keluar dari perangkap ini, Indonesia perlu mengubah paradigma pembangunan. Pertama, menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama, bukan sekadar efek samping dari pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal perlu lebih ekspansif dan berorientasi pada investasi publik yang padat karya, seperti infrastruktur hijau dan perawatan sosial. Kedua, memperkuat lembaga ketenagakerjaan dan hak perundingan buruh agar hubungan industrial lebih seimbang. Perlindungan tenaga kerja bukan penghambat efisiensi, melainkan fondasi produktivitas yang berkelanjutan.
Ketiga, mempertautkan kebijakan industri dengan strategi pembangunan manusia. Adopsi teknologi harus diiringi program pelatihan ulang berskala besar agar pekerja tidak tertinggal. Pendidikan vokasi harus diposisikan sebagai tulang punggung transformasi ekonomi. Terakhir, sektor informal perlu diformalisasi secara bertahap melalui kebijakan pajak sederhana, jaminan sosial portabel, dan digitalisasi usaha mikro.