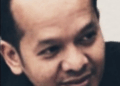Pembagian beban ongkos dan biaya pilkada kerap tidak seimbang antara kepala daerah dan wakilnya. Dalam banyak pilkada, kepala daerahlah yang paling banyak mengeluarkan biaya dan ongkos pilkada, sementara wakil kepala daerah hanya membantu. Ketimpangan pembagian beban ini juga menjadi pemicu keretakan hubungan kepala daerah dengan wakilnya. Kepala daerah yang lebih banyak mengeluarkan biaya pilkada, ketika memenangkan pertarungan, ingin menguasai semuanya, termasuk jabatan-jabatan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Kedua, ketidakjelasan visi, misi, kebijakan, dan program prioritas kepala daerah ketika pencalonan. Dokumen visi dan misi kebijakan dan program prioritas itu menjadi salah satu persyaratan yang harus diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Namun, ia tidak pernah dibuat dengan serius, apalagi melibatkan kalangan teknokratis daerah, dan benar-benar berangkat dari persoalan riil masyarakat di daerah.
Visi dan misi itu dibuat seadanya, dan sebagai pelengkap persyaratan saja di KPU. Tak pernah dihayati, diresapi, dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat di daerah. Akibatnya, setelah memenangkan pertarungan dan sudah dilantik menjadi bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, tidak tahu dan tak jelas apa yang akan dilakukan. Ia akan menjadi kepala daerah yang tuna visi dan misi. Anehnya, visi dan misi itu dicomot saja dari daerah lain. Yang belum tentu kebutuhan dan tantangannya sama.
Ketiga, ketidakjelasan ikatan koalisi dalam pencalonan kepala daerah. Koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah lebih didorong oleh ikatan kepentingan sesaat daripada kepentingan untuk jangka panjang. Parpol yang bersatu dalam pencalonan kepala daerah, persatuan itu dilakukan sulit ditemukan karena ikatan ideologis. Yang ada dibenak parpol, ketika koalisi itu dilangsungkan bagaimana porsi pembagian kekuasaan ketika pertarungan berhasil dimenangkan.
Padahal, koalisi yang sejati adalah koalisi yang berangkat dari kesamaan ideologi, bukan koalisi yang didorong oleh pembagian sumber daya kekuasaan. Koalisi jenis ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang, dan sifatnya hanya sesaat. Apabila manis kekuasaan sudah hilang, koalisi pun bubar.
Keempat, dalam pilkada yang berbiaya mahal. Sulit mencari kepala daerah yang inovatif. Kepala daerah hanya menunggu perintah dari pemerintah pusat. Tak ada program yang benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak. Padahal, dengan semangat otonomi daerah, kepala daerah mampu melahirkan kebijakan yang visioner dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Apalagi dengan pemangkasan dana transfer ke daerah membuat pemda kesulitan menentukan prioritas (Kompas, 13/10).