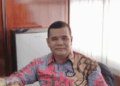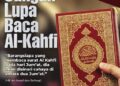Oleh: Rita Rahayu (Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)
Generasi Z lahir di masa ketika dunia berada di genggaman tangan. Mereka tumbuh dengan teknologi, terbiasa bertransaksi lewat gawai, dan hidup dalam ritme yang serba digital. Membeli kopi cukup dengan memindai kode QR, membayar tagihan tanpa uang tunai, bahkan berinvestasi hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel.
Di atas permukaan, mereka tampak sebagai generasi yang modern, cepat belajar, dan cakap dalam urusan finansial. Namun hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu.
Dalam survei terhadap 984 responden Generasi Z di Indonesia, sebagian besar adalah perempuan (63 persen) dan mayoritas masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Lebih dari 65 persen memiliki pendapatan di bawah Rp2 juta per bulan, dan hampir separuh masih tinggal di rumah orang tua. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sudah sangat dekat dengan dunia keuangan digital, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Mereka aktif dalam aktivitas ekonomi digital, tetapi belum semua memahami bagaimana mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
Penelitian ini menguji empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu financial skill, financial autonomy, financial decision making, dan financial well-being.
Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan dasar — seperti membuat anggaran, berpikir analitis, dan mengelola uang — berpengaruh besar terhadap tingkat kemandirian dan kesejahteraan finansial seseorang. Generasi yang memiliki financial skill tinggi terbukti lebih mandiri dan lebih mampu membuat keputusan finansial yang rasional. Sebaliknya, mereka yang masih bergantung pada bantuan keluarga atau tidak memiliki kebiasaan mengelola uang dengan terencana cenderung menghadapi tekanan finansial yang lebih besar.
Secara statistik, financial skill memiliki pengaruh kuat terhadap financial autonomy dengan koefisien β = 0,477 dan nilai p < 0,001. Artinya, semakin baik keterampilan keuangan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya dalam mengatur keuangan.
Selanjutnya, financial autonomy terbukti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan keuangan (β = 0,447; p < 0,001), dan keputusan keuangan yang berkualitas berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan finansial (β = 0,378; p < 0,001). Pola ini menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari keterampilan, kemandirian, dan keputusan yang terencana.
Penelitian ini juga menemukan perbedaan yang menarik antara laki-laki dan perempuan. Pada responden perempuan, hubungan antara financial skill dan financial decision making lebih kuat dibanding laki-laki. Dengan kata lain, perempuan cenderung menerapkan pengetahuan keuangan mereka secara langsung dalam membuat keputusan finansial, sedangkan laki-laki lebih banyak mengandalkan rasa percaya diri dan otonomi dalam mengelola keuangan.
Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan muda Indonesia kini mulai beralih dari pola pasif menjadi pengambil keputusan aktif dalam urusan finansialnya. Ini adalah sinyal positif bagi kesetaraan ekonomi, karena kemandirian finansial perempuan terbukti berdampak luas bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Di sisi lain, hasil survei juga mengindikasikan bahwa sebagian besar Generasi Z masih menghadapi tekanan keuangan. Rata-rata skor stres pengelolaan uang (money management stress) mencapai 2,44 untuk perempuan dan 2,65 untuk laki-laki dalam skala 1–5, menandakan bahwa banyak anak muda merasa terbebani oleh pengeluaran yang tidak terencana dan gaya hidup konsumtif.
Fenomena FOMO (fear of missing out) dan YOLO (you only live once) tampak menjadi bagian dari pola perilaku finansial mereka, yang sering kali mengarah pada keputusan impulsif.
Hasil ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Literasi keuangan di kalangan muda tidak cukup hanya mengajarkan definisi menabung, investasi, atau bunga. Yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis, merencanakan, dan mengambil keputusan keuangan yang selaras dengan tujuan hidup.
Pendidikan keuangan perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan dan karakter — bagaimana menyusun anggaran, mengontrol pengeluaran, menunda kesenangan sesaat, dan mempersiapkan masa depan.
Di sinilah peran pendidikan dan kebijakan publik menjadi sangat penting. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian keuangan sejak dini. Kurikulum literasi keuangan perlu dikembangkan secara kontekstual dan praktis, bukan sekadar teori. Mahasiswa dapat diajak membuat simulasi anggaran bulanan, mengelola uang digital, atau melakukan latihan pengambilan keputusan investasi sederhana.
Pemerintah dan lembaga keuangan juga dapat memperluas program literasi yang menyasar generasi muda secara lebih adaptif. Untuk perempuan, pelatihan yang menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan finansial bisa memperkuat peran mereka sebagai pengelola keuangan keluarga. Sedangkan bagi laki-laki, pendekatan yang menekankan perencanaan jangka panjang dan disiplin finansial akan membantu mereka terhindar dari perilaku konsumtif yang berlebihan.
Kemandirian finansial tidak hanya soal memiliki penghasilan, tetapi kemampuan mengelola hidup dengan bijak. Di tengah kemudahan teknologi yang mendorong konsumsi instan, Generasi Z perlu memahami bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, melainkan untuk dikelola dan ditumbuhkan. Dengan bekal keterampilan keuangan, otonomi, dan pengambilan keputusan yang matang, mereka dapat mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.
Generasi Z adalah masa depan ekonomi Indonesia. Jika mereka mampu mengubah pola pikir dari “menghabiskan” menjadi “mengelola”, dari “mengikuti tren” menjadi “membangun stabilitas”, maka bangsa ini sedang mempersiapkan generasi yang bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga tangguh secara finansial. (*)