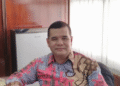Kesan wapres sebagai “ban serep” itu terlihat pada masa Orde Baru, sekalipun orang tidak meragukan kapasitas, kompetensi, dan integritas tokoh-tokoh yang menjadi pendamping politik Soeharto, seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Habibie, dan seterusnya. Corak sistem politik yang berlaku pada masa itu tidak membuka kemungkinan untuk memaksimalkan peran (jabatan) wapres, sehingga muncullah kesan wapres hanya sebagai “ban serep”.
Penyeimbang
Namun, dalam perspektif tertentu, keberadaan wapres juga berfungsi sebagai penyeimbang politik dan pemerintahan. Di awal pemerintahan republik, jika Soekarno dianggap mewakili Jawa, maka Hatta mewakili luar Jawa. Dikotomi berdasarkan politik identitas Jawa-luar Jawa ini sebenarnya secara eksplisit tidak dimunculkan sebelum kemerdekaan maupun masa awal kemerdekaan. Dwitunggal Soekarno-Hatta mencerminkan kombinasi dan keseimbangan antara tipe pemimpin “solidarity maker” dan “administrator”. (Feith, 1970)
Baru ketika Hatta mundur sebagai wapres akhir 1956, terasa ada yang kurang, timpang, atau tidak seimbang, sehingga muncul istilah “Sukar No Hatta”, yang menggambarkan kondisi politik bangsa sejak paruh kedua tahun 1950-an dan masa setelahnya. Mundurnya Bung Hatta dalam batas tertentu dianggap ikut memicu atau menambah ketidakpuasan daerah-daerah di luar Jawa hingga meletusnya peristiwa PRRI/Permesta (Leirissa, 1991).
Pasca-Hatta, Presiden Soekarno memang kemudian mengangkat tokoh seperti Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Menhankam. Nasution, dengan prestise jabatan dan pengaruh besarnya pada masa transisi dan “stabilisasi” Demokrasi Terpimpin (Crouch, 1983), bisa saja dianggap mewakili luar Jawa. Namun dibandingkan jabatan wapres, jabatan Menhankam yang dipegangnya tetap dianggap kurang representatif untuk tujuan keseimbangan politik nasional, misalnya dalam konteks Jawa-luar Jawa.
Pada masa Soeharto, keseimbangan ini nampaknya kurang menjadi perhatian, karena memang tidak merupakan tuntutan dari sistem yang berlaku maupun realitas politik. Rumusan duet Jawa-luar Jawa hanya terjadi pada saat Soeharto berpasangan dengan Adam Malik dan BJ Habibie. Ketika Soeharto memilih Sultan Hamengkubuwono IX, Sudharmono, Try Sutrisno, dan juga sebelumnya (dalam batas tertentu) Umar Wirahadikusumah sebagai pendampingnya, maka pola keseimbangan bercorak lintas-regional dan lintas-kultural dalam kepemimpinan politik nasional seolah tidak berlaku lagi.
Pada era Reformasi, politik keseimbangan tampaknya tidak lagi hanya memerhatikan keterwakilan unsur Jawa-luar Jawa, tetapi juga nasionalis-Islam atau Islam-nasionalis, terutama setelah masa singkat kepresidenan Habibie—meskipun Habibie sendiri dianggap mewakili Islam, luar Jawa, atau Indonesia Timur sekaligus. Pola keseimbangan “aliran politik” atau “politik aliran” pada jabatan presiden-wapres ini mulai berlaku pada masa duet kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri. Keduanya mencerminkan keseimbangan unsur Islam-nasionalis dan unsur gender. Setelahnya, pasangan Megawati-Hamzah Haz bahkan tak hanya mencerminkan keseimbangan nasionalis-Islam dan unsur gender, tetapi juga Jawa-luar Jawa. Bahkan spektrum politik keseimbangan pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla lebih luas lagi. Pasangan ini tak hanya merefleksikan kombinasi unsur “nasionalis-Islam”, “Jawa-luar Jawa”, atau “Indonesia Barat-Indonesia Timur”, tetapi juga unsur “militer-sipil”.
Pola keseimbangan lintas regional dan lintas primordial itu “berantakan” pada saat Presiden Yudhoyono memilih berpasangan dengan ekonom Boediono. Keduanya berasal dari etnis Jawa dan golongan nasionalis. Dalam konteks politik keseimbangan tadi, duet ini lebih mencerminkan keseimbangan “militer-sipil” di samping (dalam batas tertentu) keseimbangan “politisi-teknokrat”. Pada saat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tampil di kursi presiden dan wakil presiden, keduanya tidak hanya dapat mencerminkan komposisi Jawa-luar Jawa atau Indonesia Barat-Indonesia Timur, tetapi juga kombinasi nasionalis-Islam. Ketika pada periode keduanya Jokowi didampingi wapres KH Ma’ruf Amin, pasangan ini juga lebih mencerminkan gabungan nasionalis-Islam.