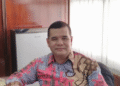Pudarnya kepemimpinan adat: Hari ini posisi ninik mamak di banyak nagari melemah, kadang hanya sebagai formalitas saja. Fungsi mereka sebagai penuntun adat mulai tergantikan oleh tokoh politik atau pemuka agama. Lemahnya proses pewarisan atau regenerasi yang terdidik secara adat, dan menurunnya penghormatan terhadap pemangku adat berdampak pada berkurangnya otoritas adat dan peran ninik mamak dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Hukum adat yang lebih mengedepankan unsur musyawarah mufakat mulai terlupakan, masyarakat cenderung berpikir untuk menempuh jalur hukum resmi dan umum, seperti pidana atau perdata.
Nagari sebagai basis budaya digantikan oleh sistem administratif: Setelah Minangkabau kehilangan pemerintahan Nagari dan berganti dengan pemerintahan Desa pada tahun 1979, maka sejak era reformasi 1999, sistem pemerintahan Nagari dihidupkan kembali, namun sering kali hanya sebagai struktur birokrasi layaknya pemerintahan Desa saja. Nilai-nilai sosial budaya yang dulu hidup dalam tatanan Nagari, hari ini tidak lagi menjadi prioritas.
Dari Perspektif Agama.
Seterusnya, kelunturan pada unsur agama. Meskipun secara statistik masyarakat Minangkabau dikenal agamis, namun ada indikasi bahwa kini praktek keagamaan mulai terpesong, yang hanya cenderung kepada ritual dan simbol-simbol saja, tidak lagi meliputi sosial spiritual yang menyeluruh, contohnya:
Dominasi pendidikan ritual yang minim etika sosial. Banyak pesantren dan sekolah Islam menekankan hafalan, fiqih ibadah, tapi kurang dalam pembentukan prilaku sosial (akhlak terhadap sesama). Dampaknya, ditemui ada di antara anak-anak hafiz yang rajin ibadah ritual, tapi kurang sopan santun budaya Minangkabau, bahkan terkadang terlihat kurang hormat. Dalam hal ini kita perlu belajar kepada Jepang.
Maraknya fenomena kemunafikan sosial. Di antara ritual, simbol dan moral tersebut, berbagai macam kasus korupsi juga bermunculan, praktik suap, dan penyimpangan moral tetap terjadi walaupun pelakunya dikenal religius secara formal. Maarif (2021) menyatakan bahwa dewasa ini banyak umat Islam yang aktif secara ritual namun tidak merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan Al‑Qur’an.
Simbolisme keagamaan lebih dominan dari substansi. Membangun masjid megah, membagikan mushaf, atau acara dakwah besar-besaran sering kali lebih menonjol, dibanding penerapan nilai sosial keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan empati. Azra (2008) menyoroti bahwa Islam hari ini makin simbolik dan dangkal jika tidak dibarengi dengan pendidikan karakter dan etika sosial.
LGBT dan seks bebas di kalangan remaja. Berdasarkan sejumlah laporan media, tidak dapat disangkal bahwa perilaku seks menyimpang seperti LGBT sudah merambah ke sejumlah pesantren dan sekolah di Ranah Minangkabau. Hal ini menunjukkan ketimpangan serius antara pengajaran agama secara formal dengan pengawasan moral dan lingkungan sosial.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua unsur inti filosofi ABS-SBK, yakni adat dan agama, yang seharusnya saling bersinergi dalam membentuk jati diri masyarakat, kini justru melemah secara bersamaan. Kelunturan ini tidak hanya mengancam eksistensi nilai budaya Minangkabau, tapi juga membuka ruang bagi krisis moral dan sosial di kalangan generasi muda.