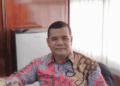Berdasarkan catatan Walhi Sumbar, hingga bulan Agustus 2024, lewat skema perhutanan sosial Pemprov Sumbar telah memberikan hak pengelolaan kawasan hutan di areal seluas 300 ribu hektare bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan.
Pemberian hak kelola bagi masyarakat melalui kebijakan perhutanan sosial ini diakuinya memang masuk akal untuk diterapkan, mengingat mayoritas desa atau nagari yang ada di Sumbar terletak di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.
Namun demikian, masifnya pemberian izin hak kelola masyarakat lewat skema perhutanan sosial justru dinilai menghilangkan dan mengabaikan aspek pengakuan dan penghormatan negara terhadap tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat Minangkabau. Pasalnya, luas hutan adat Sumbar, yang tercatat dan diakui negara, ternyata hanya 0,3 persen dari total luas keseluruhan kawasan hutan Sumbar.
“Itupun hanya ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertanyaannya, apakah di 18 kabupaten/kota lainnya tidak ada masyarakat hukum adat? Justru yang ada hanyalah skema perhutanan sosial yang notabene statusnya adalah hutan negara, yang sewaktu-waktu bisa kembali diambil alih negara jika izinnya tidak diperpanjang,” kata Wengki.
Perbedaan antara hutan negara dan hutan adat ini bahkan telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat adat. Artinya, bukan lagi sebagai hutan negara. Putusan ini mengakomodasi hak masyarakat adat dalam UU Kehutanan dengan kerangka hukum progresif.
Oleh karena itu, Walhi meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoreksi kebijakan perhutanan sosial serta memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Termasuk bagi tanah-tanah ulayat yang di atasnya telah terlanjur terbit izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit.