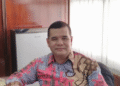OLEH : Diego Alpadani dan Irhas Widy

Sesekali Kurcang akan menatap ampu kakinya. Ia hanya bisa menutup rapat mulutnya. Bergumam pun tidak berani. Sementara perempuan berkerudung putih di hadapan masih tetap berbicara. Di sela-sela ucapan, perempuan itu akan menghirup napas panjang-panjang. Tampak dengan jelas beberapa garis wajahnya. Terutama di bagian kelopak mata. Sedikit waktu lagi kekeriputan akan menghampiri.
Sudah untuk yang ke sekian kali. Kurcang menerima wejangan panjang yang terkadang dibungkus dengan tarikan daun kuping. Dengan sangat memahami, Kurcang tak akan pernah bisa mendaceh apalagi membentak, apalagi melawan. Itu semacam ketidakmungkinan. Ia sadar bahwa itu tak akan pernah terjadi.
Pernah sekali suaranya meninggi disebabkan tidak menerima sindiran atas wejangan panjang perempuan itu. Menggelegar otaknya.
“Di luar salah, di rumah, Mak marah,” sergahnya sambil membanting benda canggih di genggaman ke atas kasur. “Sudahlah,” sambungnya.
Itu terjadi sesaat setelah emak membandingkan dirinya dengan ranting yang terserak di jalan yang masih memiliki nilai guna, setidaknya untuk menjangkau yang tidak terjangkau.
Muka Kurcang merah padam meski kulitnya sawo matang. Namun, merahnya muka dan naiknya tensi tidak bisa digelapkan. Ia melangkah menuju pintu. Menjangkau gagang pintu. Lalu diempas sekencang-kencangnya. Di balik pintu langkahnya galau bin gamang. Lekas Kurcang tersadar saat Mak menarik kuping kirinya. Bahwa bentakan dan perlawanan fisik hanyalah percobaan yang pernah terbentang luas bertriliun kali di benak Kurcang. Tidak pernah benar-benar terjadi. Hanya abstrak yang tidak pernah terealisasi.
Memang ada keinginan Kurcang membantah hal ihwal perkataan Mak. Atau, setidaknya mengemukakan pendapat tentang segala persoalan yang dijadikan Mak sebagai umpan matang untuk mengomelinya. Sebagaimana saat ini terjadi. Di meja makan setelah Kurcang makan sendirian, Mak mengomelinya tentang gaya makan yang tidak sesuai dengan tata kesopanan. Bagi Mak, laki-laki yang sopan, budiman, berakhlak baik, adalah laki-laki yang mengambil sedikit nasi. Walau selapar apa pun dan seberat apa pun hari dijalani.
Mak sangat kesal melihat Kurcang mengambil nasi segunung Marapi. Ditambah lagi, Kurcang sangat rajin memainkan gawai ketika makan. Melihat tingkah itu, Mak terbawa ragam dan geram.
Mak mengomel. Menyebutkan bahwa kakek Kurcang selalu mengajarinya tentang tata cara duduk, makan, bertamu, menerima tamu, dan banyak lagi. Kakek selalu menekankan tata cara kesopanan. Namun, Kurcang benar-benar tampak tak menerima perbandingan yang disampaikan. Baginya, zaman telah membentang luas dan meninggalkan segala kepurbaan dan kekunoan. Meski begitu, Kurcang tak akan pernah berani mengemukakan pendapat. Apalagi membentak Mak.
Ia hanya menatap ampu kaki. Sesekali mengangguk seperti burung balam mengantuk. Dan sangat jarang ia menggeleng.
“Waktu Mak sebesar kau, ekonomi susah. Di mana-mana kerusuhan terjadi. Paceklik, semua darurat. Walau waktu itu Mak tak begitu tahu apa yang didaruratkan. Nemun tetap, Mak masih ingat segala ajaran kesopanan, bahwa mengambil segunung nasi bukanlah tindakan yang benar!”
Kurcang mengangguk. Ia paham Mak sudah benar-benar seperti benda cair yang larut. Mak berada di titik didih kemarahan, tak lagi berada di riak-riak kekesalan. Dan yang lebih penting, Mak sudah masuk ke dalam mode kemasalaluan yang baginya adalah hal-hal terbaik. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Kurcang membentangkan lamunan, dalam dirinya ia berjanji tak akan mempersoalkan siapa pun untuk makan sebanyak apa pun. Selagi bisa empat gunung, kenapa harus segunung. Ia berbicara dalam hati dengan kepala masih menunduk. Tak berani menatap Mak.
Kurcang benar-benar masuk dalam miniatur realitas yang dibentuk dalam benaknya. Padahal Mak masih tetap memberikan wejangan padanya. Semua ucapan Mak terasa tak jelas, tak tentu arah, tak ada hilir-mudik, tidak terstruktur, penuh kekacauan. Ia lebih senang berdialektika dalam akalnya.
“Dunia sudah menjadi yang tak pernah terpikirkan oleh Mak,” ucap Kurcang satu dalam benak. Kurcang dua dan Kurcang tiga setuju. Dibuktikan dengan anggukan dan senyum lebar. Memberikan kedua jempol tangan.
“Setidaknya Mak harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Ini era kita, tonggak berada di jemari kita. Sekarang bukan lagi paceklik, bukan lagi darurat, kesopanan dan segala bentuk pernak-pernik kesantunan bisa berubah kapan saja,” Kurcang empat mengemukakan pendapat sejalan dan selaras dengan Kurcang satu. Kurcang satu menatap alis Kurcang empat dan tersenyum lebar.
“Pak Wo, Pak Dang, Pak Etek lewat, tak terlihat. Apalagi di sapa. Itu yang dinamakan menyesuaikan? Haram matamu sejenak, pun menyapa mereka yang lalu bahkan telah hilir-mudik di pelupuk mata,” Kurcang dua meniru gaya Mak berbicara dengan tangan kiri seolah memperbaiki jilbab.
Sebenarnya, omelan Mak adalah bentuk dari kegelisahan terhadap anaknya. Bagaimana seorang Mak bisa membiarkan seorang anak melakukan kesalahan terus-menerus. Dengan naluri keibuan yang dimiliki Mak, Kurcang harus benar-benar tahu akan ketidaktahuannya. Ia harus menuju pada hal-hal yang benar dalam kacamata kebenaran. Bukan terombang-ambing dalam kegelisahan yang tak bermoral. Walaupun itu hanya menyoal makan, duduk, bertamu, menerima tamu, dan segala macam nilai-nilai kesantunan.
Ditambah lagi, kecanduan Kurcang terhadap benda kecil dalam genggaman yang disebut gawai. Bahkan, gawai itu tidak tertinggal ketika tinja yang mendesak ingin dikeluarkan di jamban belakang. Nanar pandangan Mak melihat tingkah kurcang yang kelewatan. Kurcang sangat-sangat kecanduan dengan permainan-permainan digital di dalam gawainya.
Selain itu, Kurcang juga sering bertandang ke rumah teman-temannya hanya untuk bermain game daring bersama-sama. Bahkan hal itu dikerjakan hingga larut malam. Cara makan dan bertandang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Mak, yang tak pernah suka keseringan bertandang apalagi tidur di rumah teman.
Walau perhatian Mak hanya sebagai angin lalu. Walau wejangan Mak hanya seperti cerita-cerita masa lalu. Namun, Mak tetaplah Mak. Sebagaimana Mak pada umumnya, tak ingin anak-anaknya berada dalam ceruk ketidakbergunaan di kehidupan. Baik sekarang ataupun kelak. Bahkan Mak selalu berdoa untuk Kurcang. Selalu tanpa henti, walau Kurcang masih belum menampakkan arah perubahan seperti doa-doa yang selalu dihaturkan Mak. Terkadang Mak sering berkaca-kaca membayangkan bagaimana Kurcang kelak. Tentu banyak hal-hal terpatri dalam pikiran.
“Mak selalu begitu! Namun kata orang, Mak sangat-sangat menyanyangi. Walau selalu mengomel, menarik daun telinga. Ah, namun tetap, Mak benar-benar sayang. Ataukah harus dihitung terlebih dahulu persentase kesayangan, Mak?” ucap Kurcang tiga membuat Kurcang lainnya mengangguk-angguk persis seperti saat menerima wejangan Mak.
Kurcang satu memikirkan perkataan itu. Ia larut dalam pikirannya yang sebanarnya sudah berada dalam benaknya sendiri. Ia mengingat setiap yang bisa diingat dari Mak. Wejangan, cara bicara, bahkan cara Mak mengurangi nasi segunung yang ada di piring Kurcang. Semakin dalam Kurcang satu mengingat-ingat. Tiba-tiba telapak tangan yang sangat lembut memegang pundak Kurcang yang sedari tadi berada di kursi meja makan. Tangan itu merangkul leher Kurcang. Didekatkan keningnya ke kepala bagian belakang Kurcang.
Kucang mulai tersadar. Kurcang kembali. Lepas semua riak-riak ingatan dan mengempas inti dari hati Kurcang. Tangan halus tadi masih tetap merangkul erat leher Kurcang. Akhirnya jatuh juga butiran-butiran bening di pipi Kurcang. Di kursi dan meja makan yang saat ini Kurcang terduduk, ia hanya dapat mengingat-ingat. Merekonstruksi Mak dengan cara yang paling realita dalam pikiran.
Kurcang meraih tangan halus tadi seolah memberi pernyataan untuk melepas dekapan terlebih dahulu. Kurcang berusaha berdiri. Ia membalikkan badan. Matanya benar-benar telah merah. Ia tersenyum kepada si pemilik tangan halus tadi. Senyuman itu dibalas dengan senyuman yang sangat tulus, hingga susah dideskripsikan.
“Uda yang akan menjadi imam? Uda berikan persembahan terakhir untuk Mak. Penghormatan, sekaligus anjuran agama. Jadilah imam untuk Mak. Untuk yang terakhir kalinya,” ucap perempuan bertangan halus itu.
Kurcang tersenyum dan mengangguk pada perempuan itu. Kurcang menggenggam erat tangan perempuan itu. Sepasang suami-istri itu berjalan dengan penuh kepercayaan ke tengah rumah, ke kerumunan di tengah rumah. Tempat Mak terbujur mengarah ke kiblat. Tepat di tengah rumah sebelum di bawa ke Surau Gadang. (*)
DIEGO ALPADANI dan IRHAS WIDY. Keduanya tercatat sebagai Mahasiswa pada jurusan Sastra Indonesia, Universitas Andalas, dan aktif berkegiatan di UKMF di Labor Penulisan Kreatif (LPK).